Menuturkan Indonesia dari Fenomena Emha
Membincang fenomena Emha (meminjam istilah Halim HD) memang tak pernah ada habisnya. Pemikirannya selalu menembus batas-batas demarkasi intelektual, dimensi spiritual, bahkan standar moral di tengah-tengah masyarakat. Gerakan sosialnya pun menarik karena naluri aktivismenya yang selalu memposisikan diri di luar arus dan pagar mainstream. Energi hibrida agamawan-budayawan-aktivis-penulis-oratornya membuatnya tak pernah absen dari upaya memadukan aneka rupa senyawa estetika, religiusitas, sosial, politik, dan kultural kedalam sebuah bejana kehidupan yang tidak hanya harmonis, tetapi juga puitis dan terkadang magis.
Sebagai mahluk multidimensi yang langka, tidak mengherankan jika ia sering disalahpahami oleh banyak kalangan. Tak jarang frekuensi kepentingan orang-orang di kursi kuasa, di pucuk kharisma, dan di hulu-hilir niaga terganggu oleh dentingan Saron dan Bonang serta lautan tinta kritisisme seorang Emha. Tak sedikit pula dari mereka yang pernah aktif di lingkaran utama towaf dan jalur sa’i sosial-budaya sang ‘Kiai Mbeling’ ini datang dengan puja dan cinta namun pergi dengan iri dan dengki semata karena salah menilai Emha.
Kesalahpahaman itu mungkin wajar terjadi. Pertama karena memang ada kecenderungan kronis di masyarakat kita, ketika memandang sebuah fenomena budaya, sosial, bahkan politik dengan kacamata kuda. Kedua karena Emha ini memang tipe manusia ruang yang mampu menampung, bukan perabot yang selalu membutuhkan tempat bernaung. Trajektori hidupnya bukan sekolah-kuliah-harta melimpah-hidup mewah, tetapi nyantri-berpuisi-berdramaturgi-jalan sunyi. Ini membuat upaya untuk memahaminya harus dilakukan dengan dua pendekatan sekaligus. Dari sudut pandang etic yang selama ini sudah banyak dilakukan oleh para kritikus dan khalayak. Juga dari sisi emic yang mencoba menggali relung-relung terdalamnya yang selama ini tersembunyi.

Mbah Nun Bertutur, buku terbaru Emha yang diterbitkan Bentang Pustaka April 2021 ini menawarkan narasi emic yang sedikit berbeda tentang fenomena Emha. Buku ini bisa juga disebut autoethnography atau otoetgrafis karena seluruh isinya merupakan hasil self-reflection atas pemikiran dan pengalaman Emha sendiri sejak kecilnya hingga tiga perempat abad perjalanan hidupnya. Dari judulnya saja, ada dua nuansa utama yang tersirat. Pertama Mbah, sebuah panggilan dalam khazanah budaya Jawa yang mengisyaratkan hubungan lintas generasi, tetapi juga mengandung nilai ‘keramat’, penghormatan, tetapi juga kasih-sayang terutama dari para cucunya. Kedua bertutur, ini juga idiom Jawa yang sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dan memiliki makna amelioratif dari sekedar bercerita atau bercakap-cakap. Ada Nuansa reflektif si Mbah yang amat merindukan cucu-cucunya, dan sebaliknya, saling bertutur di gardu tengah desa menjelang senja.
Dan nampaknya, momentum pandemi Covid-19 yang sudah berlangusng lebih dari setahun ini memberikan ruang kontemplatif yang begitu tenang dan dalam bagi Emha. Berbagai macam untold stories yang selama ini tertimbun oleh padatnya jadwal keliling dan seluruh aktivitas publik yang ia jalani tanpa henti terselip di buku ini. Sejak masa kecil di Jombang, nyantri di Gontor, masa muda di Jogja yang begitu transformatif, hingga pergumulan di hampir semua arena teater sosial Indonesia di semua cita-rasa presiden yang memimpinnya, bahkan ‘penggelandangan’ pribadi dan pentas-pentasnya bersama Kiaikanjeng di seluruh benua, hampir semua tertutur singkat di sini. Ada banyak anekdot, pemaknaan baru, bahkan pengakuan faktual di sana-sini yang membuat pembaca buku ini lebih ngeh, sambil sesekali menganggukkan kepala seraya bergumam “oh…ternyata…”
Kekhasan buku-buku Emha selama ini memang seperti jembatan. Isinya kumpulan essai yang dirangkai menjadi satu buku tematis yang dalam beberapa kesempatan ia sebut berposisi diantara puisi dan artikel. Dan format ini memungkinkan jangkauan pembaca yang lebih inklusif. Namun demikian, keberpihakannya kepada wong cilik nampak tetap sangat jelas dari hampir semua judul yang diangkat di banyak bukunya, termasuk di buku ini. Sehingga kaum elit yang meskipun secara sembunyi-sembunyi ikut menikmati subliman pesan-pesan mendasar dari beragam tulisan Emha, mereka akan enggan mengonfirmasinya ke publik bahwa inspirasinya dinukil dari sana.
Etos utama bertuturunya masih sangat kentara, yaitu dengan dua nafas utama. Pertama, dekonstruksi atas doktrin agama, nilai budaya, pakem sosial, formula politik, maupun, collective believe yang berlaku di masyarakat. Kedua, kecenderungan ‘menggugat’ seluruh bentuk institusionalisasi dan formalisasi dari semua dialektika tersebut, yang dalam banyak aspek memang mengkerdirkan logika dasar kemanusiaan, persaudaraaan, dan saling menghargai sesama.
Yang menarik, berbeda dengan banyak sekali buku-buku Emha sebelumnya, buku ini lebih ‘literatif’ menggunakan rujukan tekstual agama dari Alquran maupun hadist. Ini penting untuk dicatat. Banyak intelektual Muslim berangkat dari teks agama di masa mudanya, kemudian baru menemukan pemahaman mendasar dan konteksnya di masa tua. Tetapi Emha, ia menyelami berjuta konteks untuk memahami nilai-nilai substansial agama sejak masa muda, baru kemudian merangkai simpul-simpul justifikasi teksnya di usia senja.
Dan ini mungkin yang membuat narasi bertuturnya lebih mengena, karena basis empiris di kehidupan nyatanya begitu luasnya. Dan ini pula yang barangkali membawanya ke berbagai permakluman dan permaafan kepada kedunguan siapa saja yang mendiskreditkannya, mencatut namanya, dan mengkapitalisasi ide dan kreativitasnya. Perlu diingat, ‘karir’ intelektualnya memang bukan dibangun dari kepiawaiannya menelan teori dan formula, tetapi dari meneliti setiap kata. Buku pertamanya bukan karya akademis yang jelas jarak antara penulis dan yang ditulisnya, tetapi kumpulan puisi tentang frustasi hidupnya. Judulnya saja “M” Frustasi (1975) yang mengisyaratkan betapa “Frustasi”-nya seorang e”M”ha dengan dunia seisinya.
Meskipun ada juga ekspresi-ekspresi kejengkelan atas ulah para milenial manja, atas ketidakseriusan para pemangku hajat anak bangsa, dan atas kesembronoan para cerdik pandai memilih diam seribu bahasa, Emha yang sudah menjadi ‘Mbah’ masih terus menaruh harapan besar kepada para cucunya. Mulai dari mereka yang masih setia bertani di desa-desa, yang terpaksa pergi ke kota demi nafkah keluarga, hingga para kaum papa di jalanan dan di trotoar peradaban dunia maya. Frustrasi itu sebuah energi, yang jika dituturkan akan ada kemungkinan untuk ditransformasikan. Dan energi tak pernah bisa dimusnahkan, karena ia juga tak bisa diciptakan.
Akhirnya, dengan segala analogi, imajinasi, dan empatinya, sangkan paran buku Mbah Nun Bertutur ini sebenarnya bukan tentang Emha yang menuturkan dirinya. Ini buku tentang anak bangsa yang menuturkan masa depan Indonesia.
Ulasan buku Mbah Nun Bertutur oleh Ahmad Karim
(Mahasiswa program doktoral Departemen Antropologi Universitas Amsterdam Belanda)




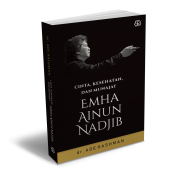


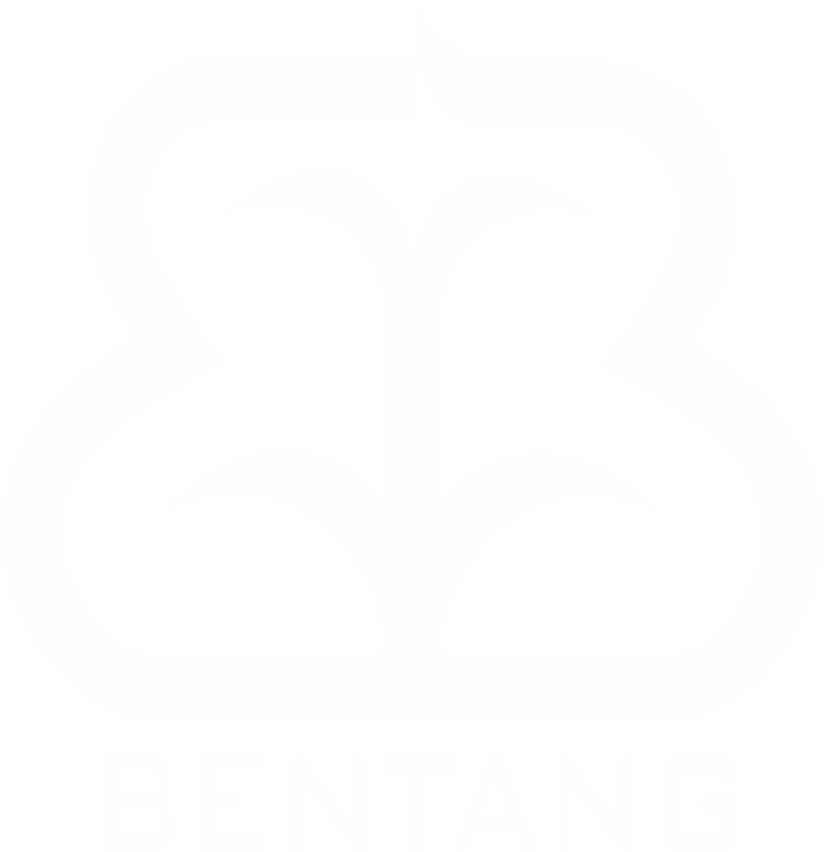





Trackbacks & Pingbacks
[…] Baca juga: Menuturkan Indonesia dari Fenomena Emha […]
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!