Orang Berpuasa atau Manusia Puasa
Puasa adalah sebuah istilah yang kita pinjam dari bahasa Sanksekerta, yakni “Upavasa”. Kata “Upa” berarti dekat dan “vas” berarti hidup. Penggabungan dua kata tersebut memiliki makna yang lebih dari sekadar menahan lapar dan dahaga, konon menurut para Resi dan Biksu, kata “upavasa” berarti hidup yang terbiasa dekat dengan Sang Pencipta melalui doa dan berpegang teguh dalam hal tersebut. Kalangan spiritualis dulu berpandangan, aktivitas yang menyenangkan fisik jasmani seperti makan, minum serta berhubungan badan sangat bersifat duniawi sehingga dipercaya cenderung menjauhkan atau melupakan kehadiran Sang Pencipta.
Dipergunakannya istilah “Puasa” dalam bahasa Indonesia (bukan Shiyam atauShoum), seperti populernya istilah “sembahyang” ketimbang sholat, menggambarkan bahwa beberapa unsur peradaban nusantara masa lalu masih diterima dalam kosakata kita, negeri yang jumlah umat Islamnya mayoritas. Penggunaan istilah puasa ini juga menjadi bukti bahwa laku berpantang makan minum ini telah berjalan jauh sebelum syariat Shiyam Ramadlan diturunkan kepada Rasulullah saw. Qur`an menegaskan …”diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu”…(QS 2:183).
Adapun istilah orisinal yang diperkenalkan Qur`an dalam konteks berpuasa adalah Shiyam dan Shoum. Keduanya dari segi bahasa bermakna “menahan”, namun bila dielaborasi lebih jauh nuansa kedua istilah itu tidaklah identik persis. Shiyam adalah menahan diri dari makan, minum dan berhubungan seks karena Allah sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Shiyam merupakan aturan administratif ibadah yang harus dijalani selama bulan Ramadlan. Sedangkan istilah Shoum digunakan Qur`an dalam konteks lain. Dalam Qur`an surat Maryam ayat 26, Ibunda Nabi Isa a.s dipesankan Allah untuk melakukan shoum, yakni menahan diri dengan tidak berbicara kepada kaumnya ketika putranya lahir tanpa ayah. Di ayat tersebut kata ‘shoum’ bahkan tidak terkait dengan larangan makan dan minum, karena pada awal ayatnya justru memerintahkan Maryam untuk makan dan minum. Secara bebas, shoum berarti menahan diri untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya berhak dilakukan.
Menariknya, ketika hendak memulai puasa, lafaz ikrar do’a memulai puasa yang populer menggunakan istilah Shoum, itu berarti antara ritual shiyam dan nilai shoum keduanya harus berjalan bersama-sama saling komplementer. Shiyam harus berkonten Shoum. Shiyam tanpa nilai shoum adalah praktik puasa yang muspra. Sebuah hadits Nabi, dikatakan ”Betapa banyak orang yang melakukan SHIYAM namun yang didapatnya hanyalah rasa lapar dan dahaga saja”. Dalam kesempatan lainnya misalnya Nabi mengatakan “Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan” Bila shiyam kita jalani selama 29 atau 30 hari di bulan Ramadlan, maka Shoumhendaknya menjadi ahklak yang dapat dijalankan sepanjang masa hidup kita. Shoum berkaitan dengan kecerdasan mental dalam mengendalikan diri.
Dalam term biologi, manusia digolongkan sebagai mahkluk omnivora: bisa makan apa saja. Meski dapat mengkonsumsi apa saja, kita membatasi diri dalam mengkonsumsi jumlah dan jenis suatu makanan, itulah shoum. Kita bisa ngomong apapun, bisa berbicara sebebas-bebasnya, tapi kita mengendalikan diri untuk lebih memilih mengatakan hal-hal yang baik-baik saja dan yang bermanfaat saja, itulah nilai shoum. Bahwa hidup tidak dijalani berdasarkan kebebasan ekstrem dan memperturuti selera saja, tapi membuat batasan-batasan yang baik dan wajar yang harusnya dijalani. Dalam kurikulum Maiyah diajarkan, hidup bukan melulu soal senang tak senang, suka tidak suka, tapi yang terpenting adalah baik atau tidak, benar apa salah.
Mengendalikan Vs Melampiaskan
Dalam suatu acara Maiyah kurang lebihnya Mbah Nun pernah menyampaikan bahwa: “ibadah puasa pada hakikatnya merupakan aturan yang sangat dibutuhkan manusia, tapi aslinya tidak disukai manusia”. Tidak enak itu rasanya menahan lapar, tidak mudah itu menahan dahaga, tidak enak pula kenapa harus diatur-atur bergaul dengan pasangan yang sah, kenapa harus bersahur bangun dini hari, kenapa harus ada batasan-batasan, pengekangan, pagar dan rambu-rambu? Lebih tepatnya, praktik berpuasa itu aslinya tidak disukai oleh kecenderungan syahwat manusia. Diwajibkan puasa Ramadlan itu telah menjelaskan bahwa metode ini pada dasarnya tidak kompatibel dengan syahwat, keinginan daan nafsu. Bila memang secara default sesuatu itu disenangi, maka tanpa disuruh-suruh atau diwajib-wajibkanpun akan dijalani manusia secara suka rela. Buat manusia, “mengendalikan diri jauh lebih sulit ketimbang melampiaskan keinginan” Argument-argumen dari hikayat genealogis, fakta fisiologis, kecendrungan psikologis akan mendukung pandangan ini.
Sejak bayi, anak manusia sudah terbiasa melampiaskan apa yang ia inginkan. Bila ingin makan dan minum anak bayi akan menangis menuntut dipenuhi segera keinginannya secara instant. Dan bayi memang berhak atas itu. Bila sang bayi akan buang hajat, ia akan lakukan kapan saja dimanapun saja, tanpa perlu minta izin. Beranjak kanak-kanak, keinginan itupun semakin berkembang. Lihatlah bagaimana seorang anak akan “setengah memaksa” atau bila perlu merajuk, merengek untuk dibelikan sesuatu yang ia sukai walau sebenarnya tidak ia butuhkan. Orangtua yang memiliki konsep parenting dalam mendidik anak, tentu tidak akan pernah memenuhi segala keinginan anaknya, meski mereka sanggup memenuhinya.
Bercermin dalam hikayat leluhur pun, pelanggaran yang dilakukan nenek moyang manusia, Adam di surga juga berhubungan dengan “ketidakmampuan mengendalikan diri”. Syahdan Adam dan Hawa dahulunya berdiam di surga, dan di sana mereka bebas untuk menikmati apapun fasilitas yang ada di taman syurga kecuali satu saja, “hanya sebuah pohon!”. Larangan yang “hanya satu” itu pun pada akhirnya dilanggar! Pesan moral dari kisah itu menjelaskan bahwa: dasar kelemahan manusia adalah ketidakmampuan mengendalikan diri. Maka kita sebagaimana leluhur kita, juga punya kecenderungan yang sama yakni gampang tergoda. Kita semua punya kemungkinan melanggar larangan Allah, melupakan janji setia kita dahulu dan kemudian akhirnya tergelincir jatuh tidak terhormat. Kita dapat saja terkecoh oleh sesuatu yang sepintas lalu menyenangkan dan menarik, padahal di belakang hari nanti akan membawa malapetaka. Kita semua bani Adam ini punya potensi untuk jatuh tidak terhormat kalau kita tidak tahu batas & tidak bisa menahan diri.
Dan bila merujuk pada sistem anatomi dan fisiologi manusia, lagi-lagi kita akan menemukan simpulan bahwa “pengendalian itu jauh lebih sulit dari pelampiasan”. Mekanisme kontrol tubuh manusia dilakukan oleh sistim syaraf, yang terdiri dua bagian besar yakni syaraf sadar dan syaraf otonom (tidak sadar). Syaraf otonom ini mengontrol dan mengendalikan seluruh mekanisme internal didalam tubuh kita, sejak denyut jantung, gerakan usus atau kandung kemih hingga reflek-reflek penyelamatan diri. Sistem ini dibagi atas dua bagian, syaraf simpatis dan syaraf parasimpatis; yang bekerja secara antagonis. Simpatis bekerja “memacu”, parasimpatis berfungsi “mengendalikan”. Analogi kerja tersebut, mirip-mirip fungsi gas dan rem dalam sebuah kenderaan. Tanpa gas, kenderaan tak mungkin berjalan. Semakin pedal gas ditekan dalam maka laju kecepatan kenderaan semakin tinggi. Namun kenderaan yang berjalan tanpa rem jelas membahayakan penumpang. Faktanya kemudian, tidak seperti syaraf parasimpatis yang semakin menurun kemampuannya sejalan dengan pertambahan usia, syaraf simpatis relatif tetap terpelihara. Dus, karena itu syaraf parasimpatis ini perlu “dilatih” agar ia tetap dapat menyeimbangkan kerja simpatis yang mendorong dan memacu irama kerja tubuh. Kerja simpatis yang berlebihan dan tidak diimbangi, lamban laun segera akan menghancurkan konsitusi kesehatan, menurunkan imunitas dan mempercepat proses penuaan. Ibarat kenderaan yang hanya memiliki pedal gas, sementara remnya blong maka kehancuran dari kenderaan itu mernjadi hal yang tidak terelakkan. Bukti-bukti empiris lainnya masih banyak lagi untuk membuktikan bahwa mengendalikan diri itu jauh lebih sulit dari melampiaskan diri.
Relevan dengan ini, dari madrasah Ramadlanlah kita dapat memperoleh pelatihan-pelatihan untuk self control tersebut lewat BERPUASA. Ramadlan tidak saja disebut sebagai bulan suci, tapi juga bulan yang mensucikan. Kata “Ramadlan” sendiri secara generik bermakna “membakar”. Kita selalu menemukan asosiasi dari kata “membakar” dengan pembersihan atau membentuk suatu yang baru untuk meningkatkan suatu fungsi. Sebagai contoh misalnya, sampah bila dibakar akan bersih, makanan bila dibakar (dioksidasi) akan menghasilkan energi, logam bila dibakar dapat diubah menjadi mesin atau bentuk lainnya seperti pesawat yang memiliki manfaat lebih besar untuk dipergunakan dalam kehidupan. Sebulan di gembeleng dalam institusi ramadhan, kita dilatih untuk mengontrol diri ini, dididik menahan keinginan untuk dapat menanamkan nilai-nilai shoum dalam dimensi yang lebih luas dan komprehensif.
Mbah Nun pernah mengungkapkan ilustrasi betapa uniknya ibadah puasa ini dibandingkan model-model ibadah lainnya dalam hal relasi kita dengan dunia. Jika dalam sholat kita menginterupsi dunia sejenak- saat takbiratul ihram kita memutus matarantai komunikasi sosial untuk fokus beraudiensi dengan sang Pencipta. Interupsi itu kemudian berakhir saat kita mengucapkan salam ke kanan dan kekiri, menegaskan bahwa kita siap membawa pesan damai ke seluruh lingkungan kita. Jika melakukan zakat, dunia malah kita cari, agar sebagian perbendaharaannya nanti bisa kita distribusikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Sementara ketika berhaji, kita sudah talak tiga dengan dunia. Kita tinggalkan kampung halaman sanak famili handai tolan, dengan berbekal kain putih sederhana tak berjahit kita sambut panggilan ilahi pergi ke tanah suci menyeru labbaik allahuma labbaik tanpa atribut duniawi apapun. Namun ketika berpuasa, dunia tidak kemana-mana melainkan ada dihadapan kita, NAMUN KITA TIDAK DIPERKENANKAN UNTUK MENYENTUHNYA. Pesan moralnya adalah apabila suatu ketika dunia datang dengan segala glamour kemilaunya menggoda prinsip-prinsip hidup dan idealisme kita, puasa telah menanamkan pada diri kita sebuah imunitas, ketangguhan mental dalam mengendalikan diri terhadap segala godaan dunia.
Kurikulum pendidikan Shiyam Ramadlan dalam 3 jenjang
Selama sebulan atau tiga puluh hari berpuasa ini, para ulama sering membagi puasa menjadi 3 bagian dalam rentang per-10 hari-an, yang memiliki titik tekan dan pencapainnya masing-masing. 10 hari pertama adalah masa adaptasi secara fisik, yakni jenjang puasa jasmani (berdimensi fisik). Inilah periode saat beradaptasi terhadap irama jadwal makan yang baru saat sahur dan waktu berbuka, juga penyesuaian dalam konteks mengurangi jumlah asupan makanan. Demikian pula ada adaptasi biologis terhadap irama tidur. Periode ini mewakili fase pendisiplinan terhadap fisik jasmani kita.
Dalam dunia kesehatan, kini telah terbukti luas manfaat puasa bagi kesehatan jasmani. Penelitian terbaru misalnya, Prof.Dr.Noboru Mizushima dari Tokyo Medical University mengatakan “orang yang menjalani proses kelangkaan makanan, ia telah memfasilitasi mekanisme daur ulang bagi sel-sel didalam tubuhnya untuk menyapu sel-sel yang aus dan rusak. Dalam tinjauan biokimiawi terbaru, berpuasa itu mengaktifkan proses autofag seluler (pencernaan sampah dalam sel) & apoptosys, mengakibatkan terjadi proses detoksifikasi dengan membersihkan sampah-sampah seluler (zombie sel).”. segudang fakta klinis lain yang akan panjang lebar untuk membahas hikmah puasa dari kesehatan ini. Dan bukankah Rasulullah saw sendiri juga mengatakan secara eksplisit “Berpuasalah niscaya kamu sehat”.
Pada 10 hari kedua, diharapkan kita naik kelas masuk pada fase jenjang puasa nafsani (berdimensi psikologis). Di fase ini kita melatih kedisiplinan diri khususnya dari segi mental kejiwaan. Dari segi psikologis, puasa tentu tidak sekedar menahan makan dan minum atau sekedar persyaratan sah secara fiqih saja. Namun puasa harus disertai peningkatan pemahaman tentang apa yang sesungguhnya harus kita tahan selama kita menjalani ibadah shiyam ini. Nabi saw menjelaskan keharusan yang semestinya dijalani melebihi sekedar makan minum dalam berpuasa ini dengan mengatakan “Puasa bukan hanya menahan makan dan minum saja. Tetapi puasa adalah menahan diri dari lagwu dan rofats. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya ‘Aku sedang berpuasa, sedang puasa””. Mengontrol emosi, meninggalkan perbuatan yang tidak produktif, menjauhi aktivitas yang tidak menambah nilai kemanusiaan, meninggalkan perbuatan-perbuatan negatif lainnya seperti : dusta- perilaku kasar agresif- bergihibah- berdusta- mengumpat- berkata-kata kosong dsb.
Puasa yang tidak memberi dampak terhadap fisik dan kejiwaan, hanyalah puasa yang ibaratnya hanya mengubah jadwal makan minum & istirahat saja. Kini popular istilah sinisme dalam dunia politik :”kampret vs cebong”. Saya tergoda untuk merenungkan, bagaimana bila fenomena istilah cebong-kampret ini bukan sekadar meme sarkastik politik? Bagaimana jika ini sebuah pertanda isyarat atau amsal zaman? Yang jelas menjadi cebong dan kampret di dunia hewan adalah suratan Ilahi, itu merupakan kemuliaan bagi mereka. Tapi berlaku seperti cebong atau kampret, atau mengatribusikan percebongan dan perkampretan pada manusia adalah pelecehan terhadap kemanusiaan.
Dalam kaitan dengan puasa, hindarilah “model puasa kampret dan cebong”. Kampret berpuasa pada siang hari, namun justru “berpesta pora” divmalam hari. Manusia adalah makhuk diurnal bukan species nokturnal seperti kampret. Sistem pencernaan manusia secara fisiologis dirancang untuk mengkonsumsi secara baik bagi kesehatannya pada siang hari bukan pada malam hari. Jadi berpuasa disiang hari dan melampiaskan konsumsi dimalam hari adalah seperti pola kampret yang nokturnal.
Lalu bagaimana pula model puasa yang dijalani kecebong? Ternyata menurut literatur, kecebong yang aslinya mahkluk herbivora ketika mengalami krisis makanan berubah tabiatnya menjadi pemakan segalanya bahkan bersifat kanibalis (memangsa saudaranya sendiri) Ramadlan-lah saatnya kita kembalikan marwah dan kehormatan manusia dengan tidak melabel pada sesame saudara-saudara kita dengan gelar-gelar yang tidak simpatik yang menurunkan derajat kemanusiaan.
Dan pada 10 hari ketiga terakhir, diharapkan kita akan sampai pada level yang bersifat Rabbany (level spiritual), yakni perolehan prestasi secara ruhani. Dengan mujahadah (berjuang sungguh-sungguh) kita berharap meraih pencapaian prestasi ruhani itu seperti yang disimbolkan dalam pertemuan dengan Laylat al-Qadr. Laylat al-Qadr sendiri digambarkan sebagai malam yang mampu “melipat ruang dan waktu secara quantum” yang analog dengan waktu bernilai lebih baik dari 1000 bulan. Tentunya bagi yang mendambakan ampunan Ilahi, limpahan pahala dan kesempatan melipatgandakan kebaikan, dan merindukan perjumpaan dengan Tuhannya, malam Laylatul Al-Qadr merupakan moment yang sangat istimewa dan ditunggu-tunggu..
Bila kita mampu melampaui tiga jenjang hirarki dalam per-sepuluhan disaat Puasa maka diharapkan saat memasuki satu Syawal kita akan terlahir kembali menjadi manusia atau disebut menjemput kembali fitrah asli kemanusiaan kita. Jika Ramadlan bermakna “membakar”, maka Syawal secara generik artinya “meningkat”. Diharapkan memasuki bulan Syawal terjadi peningkatan kwalitas diri, penambahan bobot kepribadian bukan peningkatan berat badan. Hidup harus dijalani secara progresif berubah hari demi hari waktu demi waktu menuju perbaikan. Orang beriman pantang berprinsip “aku masih seperti yang dulu”. Para muballigh sering membuat perumpamaan, jika pada Bulan Sya’ban kita masih seperti ulat yang rakus dan menjijikkan maka memasuki Ramadlan kita di gembleng-ditatar-dididik dengan institusi Ramadlan untuk menjadi kepompong, hingga pada akhirnya memasuki bulan Syawal kita laksana menjadi kupu-kupu yang berpenampilan indah dan membawa kemanfaatan bagi kehidupan.
Dan sesungguhnya, nilai puasa (shoum) sebenarnya baru akan teruji dan dimulai justru ketika Ramadlan berakhir.
Wallahu’alam bi al shawab.
Sangatta, 12 Mei 2019
Artikel ini ditulis oleh dr. Ade Hahsman, Sp. An. dan pertama kali dipublikasikan di https://www.caknun.com/2019/orang-berpuasa-atau-manusia-puasa/


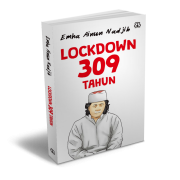





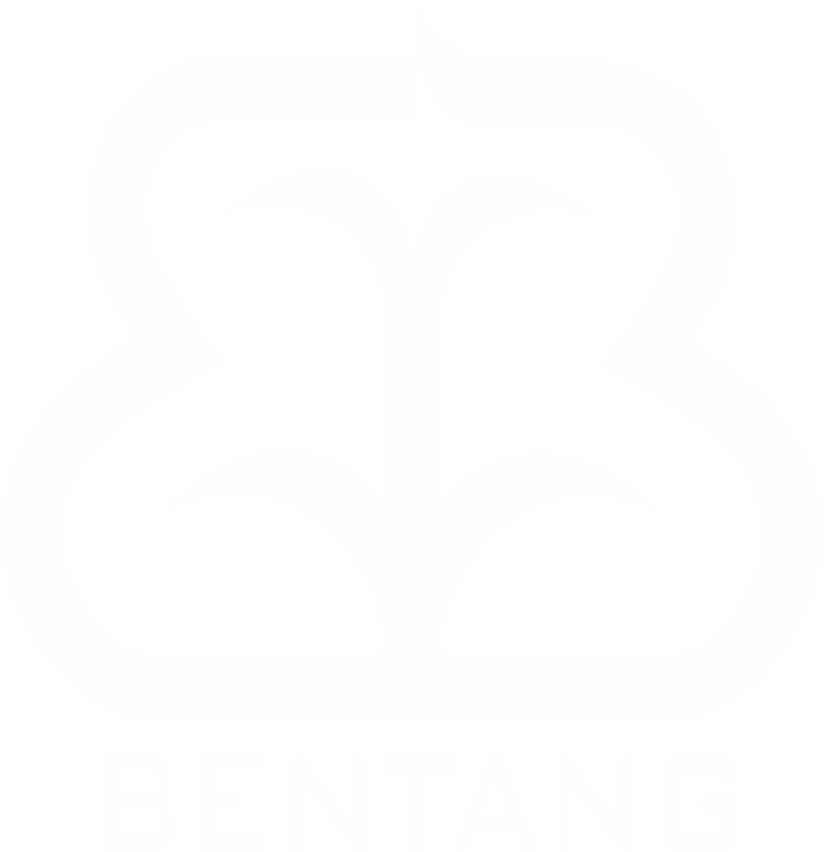






Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!