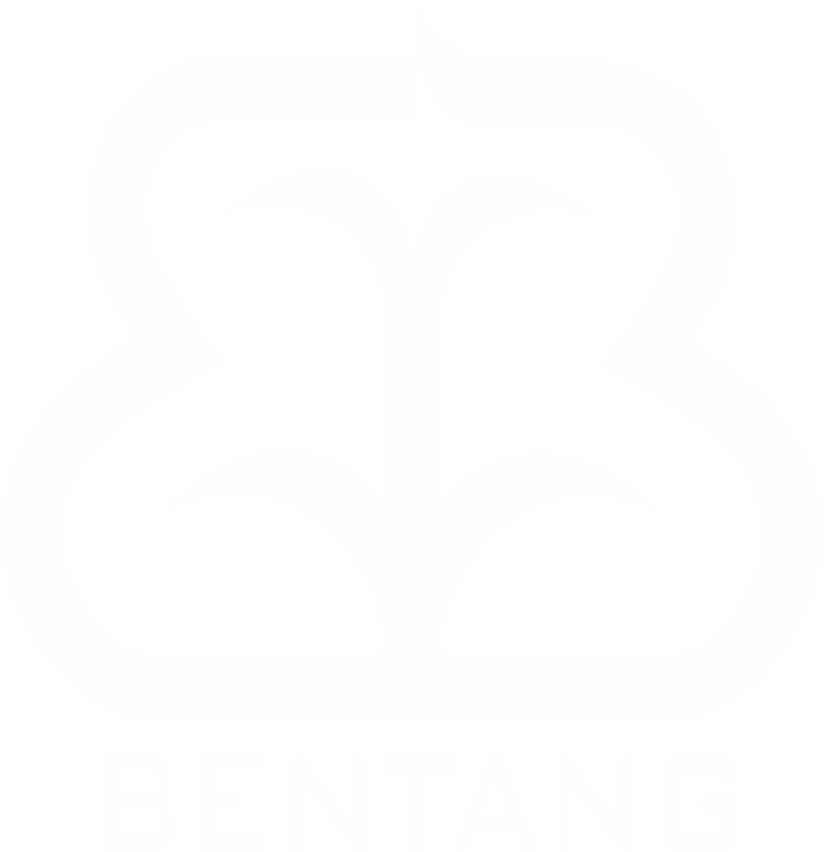Mbah Nun Bertutur: Ungkapan Emha tentang Jati Diri Bangsa yang Terkikis
/
0 Comments
Emha Ainun Nadjib dalam karya terbarunya yang berjudul Mbah…

Kata Mbah Nun tentang Bangsa Indonesia
Apakah kamu termasuk salah satu orang yang kerap memikirkan…
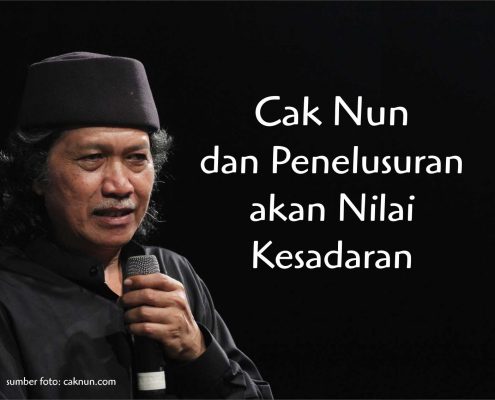
Menuturkan Indonesia dari Fenomena Emha
Membincang fenomena Emha (meminjam istilah Halim HD) memang tak…

Memaknai Kehidupan dengan Mbah Nun Bertutur
Bukan Emha Ainun Nadjib namanya jika tulisan-tulisannya tidak…
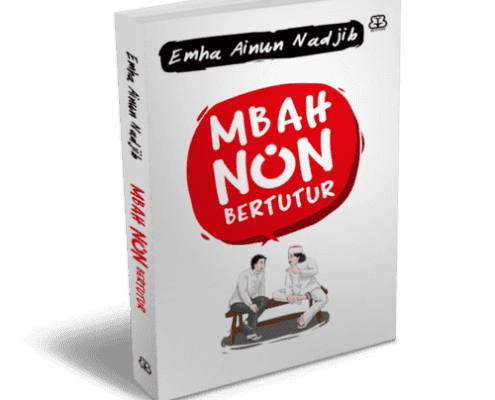
Karya Baru Emha Ainun Nadjib: Mbah Nun Bertutur
Jika kamu bertanya-tanya buku apa yang cocok, karya terbaru Emha…
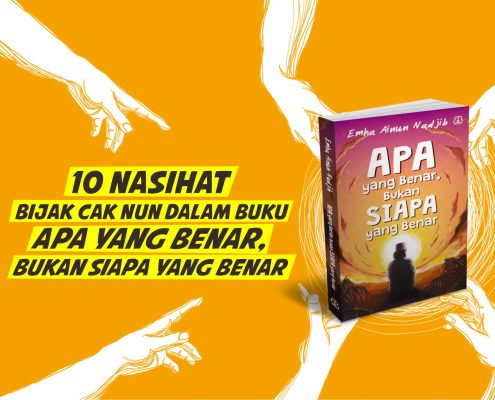
10 Nasihat Bijak Cak Nun dalam Buku Apa yang Benar, Bukan Siapa yang Benar
Tak bisa dimungkiri, setiap nasihat bijak dari…

4 Ikon Bersejarah Yogyakarta yang Disebut dalam Buku Terbaru Cak Nun
Yogyakarta selalu memiliki tempat di hati orang-orang yang…

4 Tips Produktif Menulis ala Emha Ainun Nadjib
Hingga saat ini, Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) telah…
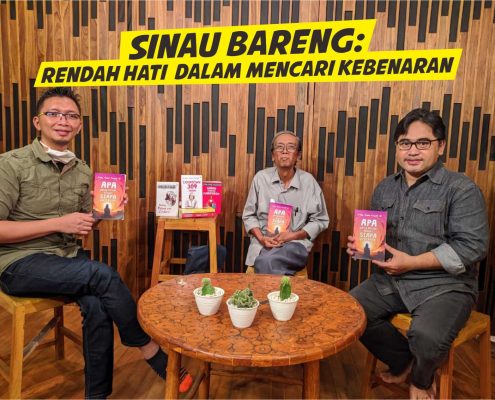
Sinau Bareng: Rendah Hati dalam Mencari Kebenaran
Pada masa pandemi ini, salah satu hal yang tentunya…
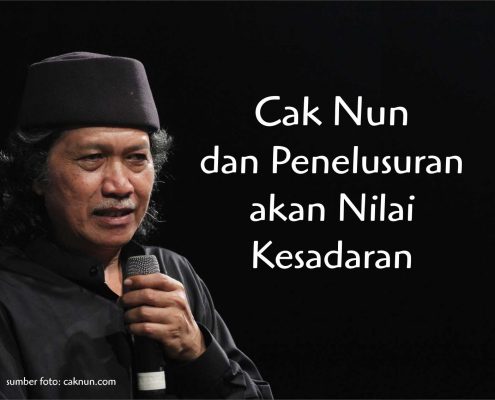
Cak Nun dan Penelusuran akan Nilai Kesadaran
Cak Nun memang pantas menyandang gelar "penulis…