Yogyakarta dan Cak Nun dalam Buku Terbaru
Yogyakarta dan Cak Nun: Tak hanya tersusun dari akar “kenangan”, daun “nyaman”, dan buah “rindu”. Lebih daripada itu, Yogyakarta menawarkan filosofi kehidupan yang begitu mendalam saat Cak Nun menuangkan kisahnya dalam buku terbaru.
—
Yogyakarta dan Cak Nun, sering kali ketika kita mendengar kota tersebut―atau bahkan sudah sering mengunjunginya―akan terbayang dengan segala romantisme yang dibuat oleh masyarakat. Namun, tidak salah, kok, ketika kita menaruh pikiran bahwa Yogyakarta hulu dan hilirnya dari sebuah kerinduan. Bahkan, banyak orang pula yang mengeklaim bahwa Yogyakarta memberikan kenangan yang begitu besar, bisa kenangan baik maupun buruk saat ditinggal pasangan.
Meskipun demikian, satu hal yang perlu tetap kita lekatkan dalam benak bahwa Yogyakarta tersusun pula dari historikal budaya, sejarah, dan banyak angan para pendahulu untuk tetap mengukuhkan segala jati diri, meskipun zaman terus bergerak. Kisah Yogyakarta dalam penuturan Cak Nun dimulai dari kaki Gunung Merapi, bersama ketiga anak-cucunya, Beruk, Gendhon, dan Pèncèng.
Beruk, Gendhon, dan Pèncèng
Yogyakarta dan Cak Nun: Mengambil hari khusus, Cak Nun menyeret ketiga anak-cucunya pada tengah malam untuk naik ke leher Gunung Merapi. Pasukan khusus dan elite SAR-DIY diminta Cak Nun mengantar dan mengawal mereka berempat. Sebab, mustahil bagi Cak Nun dan ketiga anak-cucunya untuk bisa sampai ke sana tanpa bantuan mereka.
Berhenti di suatu titik, mereka berempat duduk di sekitar semak-semak. Cak Nun mempersilakan anak-cucunya duduk melingkar, bersila, berjajar, menghadap ke selatan, mengarahkan pandangan jauh ke depan.
“Dari tempat duduk kita saat ini, semua arah di jagat raya ini serba-remang. Ada banyak sosok makhluk, tetapi samar-samar. Wujudnya bercampur dengan bayangan-bayangan wujud yang terdapat di dalam rekaman urat saraf otak kita. Bayangan itu kita dapatkan dari pengalaman-pengalaman budaya, pengetahuan, dan ilmu kita selama ini,” ucap Cak Nun sebagai awalan diskusi mereka.
Cak Nun beranjak dari tempat duduknya dan berdiri sembari membenahi cara duduk ketiga anak-cucunya itu. Seraya mengatakan, “Pandang lurus ke depan. Jangan mengharapkan cahaya terang akan datang dari seluruh ruang yang kalian pandang. Cahaya hanya bisa kalian terbitkan dari lubuk kedalaman jiwa kalian sendiri.”
Lanjut Cak Nun, “Juga mana wujud nyata mana bayangan, mana kesunyatan, mana khayalan. Jangan andalkan objek-objek itu untuk menginformasikan kepadamu. Berangkatlah dari ‘ainulyaqin batinmu sendiri. Sekarang, temukan garis dari puncak Merapi di belakang ubun-ubun kalian, ke Tugu, jalur Margo Utomo, Malioboro, Margo Mulyo, Pangurakan, Keraton yang di kawal depan belakang oleh dua alun-alun, sampai Nggading. Terus lanjut lurus ke selatan, menyentuh pantai, dan teruskan sampai ke bangunan Keraton jauh di lepas pantai, yang mengambang bukan di atas air samudra, melainkan di tlatah kesadaran nilai dalam diri kalian.”
Ketiga anak-cucu Cak Nun sangat khusyuk menjalani panduan dari beliau, meskipun Cak Nun tahu, sebenarnya anak-cucunya itu tidak paham-paham amat. Ketiga anak-cucunya itu tidak pandai, ataupun waskita, tetapi yang paling Cak Nun sukai yaitu, mereka bisa sungguh-sungguh dan tekun dalam menjalani sesuatu. Kesetiaan tidak diletakkan sebagai nilai primer di konstitusi, kurikulum sekolah, serta sistem ilmu apa pun di kalangan kelas orang-orang pandai.
Baca Juga: Petuah Jawa dari Cak Nun: Rumongso Biso atau Biso Rumongso
Patrap dan Atlas Nilai Yogya
Yogyakarta dan Cak Nun: Akhirnya semua bubrah. Jadi, mereka semua sekarang duduk melingkar.
Lalu, tiba-tiba Gendhon menanyakan, mengapa malah mereka di sini membuat atlas? Cak Nun tetap menjawab meskipun sesungguhnya mereka itu sudah paham. Namun, pengetahuan tidak bisa diketahui kebenarannya kalau tidak terletak pada koordinat ruang dan waktu yang tepat. Orang Yogya menyebutnya patrap.
Kita sudah berproses 71 tahun menjalani pem-beradab-an bangsa. Kita sudah menanam dan membangun ilmu-ilmu, demokrasi, republik, supremasi hukum, sampai ada variabel-variabel yang membumbui keadaan ini secara sangat riuh rendah. Sejak sosialisme dan kapitalisme, politik kanan dan kiri, kebudayaan timur dan barat, hingga racikan-racikan yang bikin kita kelewat pedas, lantas muncul liberalisme dan ultranya, radikalisme, fundamentalisme, ekstremisme, anarkisme, agama garis lurus, mazhab garis lengkung, politik lipatan dan strategi tikungan, serta bermacam-macam lagi.
Bahkan, kita sudah memasuki era penggandaan pahala, emas, uang, bahkan penggandaan kepribadian: pendirian yang mudah berubah, beda ucapan dengan tindakan, bermalas-malasan, tidak kukuh, hipokritisi, oportunisme, kemunafikan, bajing loncat, dan beratus gejala dan fakta sejarah lainnya.
Semua itu soal patrap. Ada yang memang memilih kebenaran versi sendiri, ada yang mengeklaim atau memanipulasi kebenaran orang banyak, ada yang tersingkir karena mencari kebenaran sejati, tetapi susah banget untuk sesuai tatkala diterapkan. Sebab, seluruh konstruksi nilai zaman ini memang sudah semakin kehilangan patrap.
Perihal atlas itu sebenarnya awal dari hilirnya. Atlas, kan, tidak hanya geografis teritorial. Manusia juga sangat memerlukan atlas nilai. Peta nilai yang dipijaknya, yang mengepungnya, kemudian bagian yang dipilihnya. Yogya perlu mengatlaskan kembali tatanan nilai diri ke-Yogya-annya karena Yogya paling berkewajiban dan menyiapkan diri untuk nanti menyelamatkan Indonesia yang sedang semakin kehilangan patrap.
Lembah Masa Depan
Yogyakarta dan Cak Nun: Kata “Yogya” sangat sensitif bagi ketiga anak-cucu Cak Nun. Menggetarkan hati dan menaikkan adrenalin. Kalau mereka berempat berdiskusi dan berkhayal tentang masa depan Yogya, bisa semalaman atau sesiangan atau sekurang-kurangnya berjam-jam. Tidak terbatas pada eksplorasi tafsir tentang keistimewaan Yogya―tentang beda antara Yogya Kota Budaya dan Yogya Ibu Kota Kebudayaan Indonesia.
Beribu dimensi tematik Yogya yang skala besar maupun kecil. Yang substansial maupun yang ilustrasional. Yang prinsipil maupun yang romatis. Yang kultural maupun spiritual. Yang samar-samar maupun yang bersahaja. Yang bumi maupun langit. Sudah Cak Nun bayangkan wilayah-wilayah tugas yang perlu dieksplorasi oleh ketiga anak-cucunya.
Itulah secuplik kisah Yogyakarta dalam tuturan Emha Ainun Najib di buku terbarunya, Apa yang Benar, Bukan Siapa yang Benar. Ikuti masa pra-pesan dari 24 Juli―9 Agustus 2020 di reseller kesayangan kalian atau melalui laman etalase Cak Nun Mencari Kebenaran. Dapatkan harga spesial, totebag, dan tanda tangan digital dari Cak Nun!
Salam,
Anggit Pamungkas Adiputra

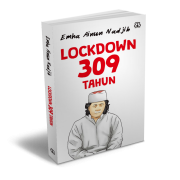





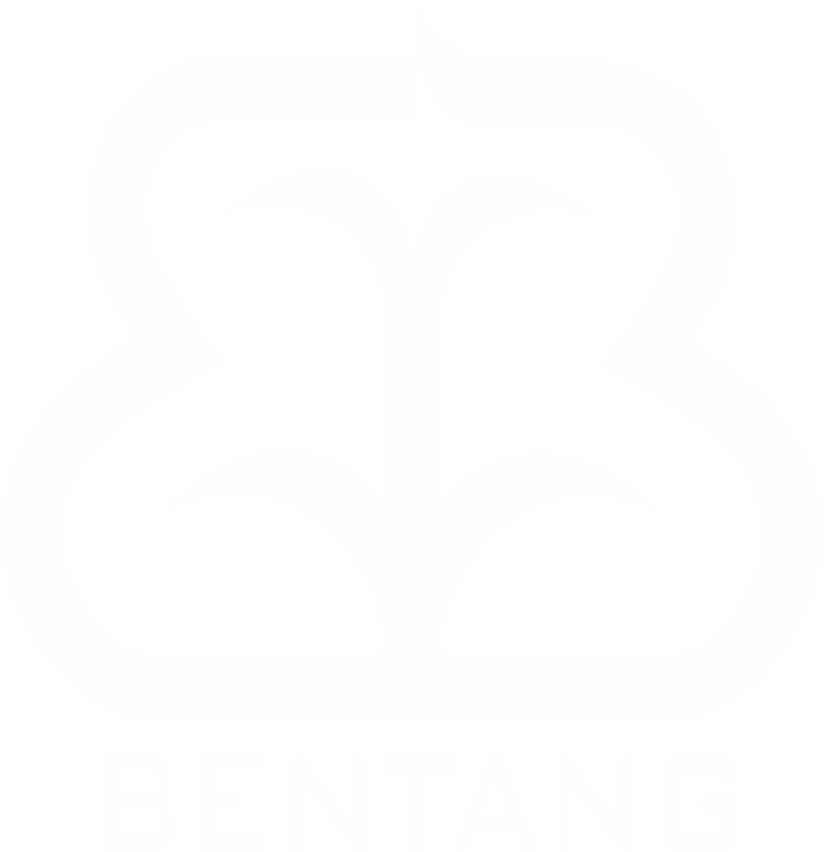






Trackbacks & Pingbacks
[…] kesadaran ini. “Dalam buku ini, diceritakan bahwa Simbah mengajak tiga anak masa depan ini ke lereng merapi. Mereka diminta untuk melihat secara luas dan memunculkan ide-ide yang bisa dijadikan pedoman untuk […]
[…] Baca Juga: Yogyakarta dan Cak Nun dalam Buku Terbaru […]
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!