Politik Identitas dan Demokrasi Liberal
Francis Fukuyama, ahli ekonomi politik yang fenomenal lewat buku The End of History and the Last Man kembali dengan karya terbarunya mengusung isu politik identitas. Buku edisi aslinya terbit 2018 dan edisi Bahasa Indonesia pada Maret 2020. Adanya edisi Bahasa Indonesia ini nampaknya karena Fukuyama termasuk salah satu ilmuwan AS yang pemikiran-pemikiran cukup dikenal di kalangan intelektual kita.
Seperti dikatakannya di bagian awal, penulisan buku Identitas ini dipicu kemenangan Donald Trump dalam Pilpres AS November 2016. Ia terkejut sekaligus terusik akan implikasinya terhadap negara adidaya itu dan dunia. Hasil Pilpres AS tersebut merupakan kejutan elektoral kedua tahun 2016 setelah hasil referendum keluarnya Inggris dari Uni Eropa.
Namun ia tidak sedang membahas “kemurungan” perkembangan demokrasi di AS, Inggris atau Eropa saja. Pada mulanya Fukuyama memang terusik oleh kemenangan Trump, yang tak hanya dianggapnya sebagai produk, tetapi juga kontributor atas fenomena membusuknya lembaga modern yang dapat mengancam prospek konsensus demokrasi liberal. Namun diagnosanya melintas ruang dan waktu menelusuri asal usul masalah yang menjadi ihwal “pembusukan” dimaksud, termasuk di negara yang demokrasinya sudah mapan seperti AS dan Inggris.
Fukuyama banyak menyorot apa yang disebutnya sebagai fenomena bangkitnya identitas dan politik identitas di berbagai belahan dunia. Menurutnya, pasang naik identitas dan politik identitas bermula dari tuntutan pengakuan atas martabat (thymos) pada konteks individu maupun kelompok, yang perspektif sejarahnya ditarik jauh ke zaman Plato, namun menjadi masalah ketika para tokoh nasionalis populis dekade kedua abad 21 mempolitisasinya untuk mendapatkan kekuasaan berbiaya “murah”.
Akibatnya, corak pengakuan universal dalam konsep demokrasi liberal kemudian ditantang oleh bentuk tuntutan pengakuan lebih sempit berdasarkan atas bangsa, agama, sekte, ras, etnis, atau gender yang kemudian justru mengakibatkan munculnya populisme anti-imigran, kebangkitan Islam yang terpolitisasi, serta fraksi-fraksi yang terpecah belah. Ia mengurutnya dari peristiwa gelombang Musim Semi Arab, Brexit, kampanye “American First” Donald Trump hingga Gerakan #MeToo yang memperluas pemahaman populer tentang kekerasan seksual.
Ia mengatakan nasionalisme maupun agama tidak akan menghilang sebagai kekuatan dalam politik dunia, khususnya dalam sistem demokrasi liberal, karena sistem ini belum sepenuhnya menyelesaikan masalah thymos, bagian jiwa yang membutuhkan pengakuan. Fukuyama kemudian “menawarkan” semacam penguatan identitas nasional inklusif yang dapat menjawab tuntutan pengakuan martabat sekaligus meredam potensi merebaknya politik kebencian, khususnya di negara-negara demokrasi liberal dan multikultur.
Fukuyama dan buku ini memang tak kurang mendapatkan kritik. Salah satu pertanyaan muncul: apakah Fukuyama masih konsisten dengan ramalannya mengenai “Akhir Sejarah” sebagai kemenangan demokrasi liberal? Fukuyama membela diri, apa yang dikatakannya seusai Perang Dingin awal 1990-an itu masih terkoneksi dengan pengamatannya atas keadaan politik sekarang. Ia malah menyebut para pengkritiknya tak memperhatikan esai asli tentang “akhir sejarah” memiliki tanda tanya di akhir judul dan di antara mereka tidak membaca bab-bab selanjutnya. Tak mengejutkan, pada ujungnya Fukuyama masih meyakini masa depan demokrasi liberal, sekalipun dengan segala tantangan dan ancamannya.
Apa relevansinya dengan Indonesia? Gejala politik yang diangkat dalam buku ini cukup kontekstual dengan fenomena politik yang terjadi di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Di negeri kita politik identitas dengan corak baru juga menguat khususnya sejak Pilkada Jakarta 2017 lalu. Tak heran, Fukuyama dalam bukunya ini juga sekilas menyinggung kasus politisasi agama yang “korban”-nya adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang beragama Kristen dan beretnis Tionghoa (h.86).
Walaupun dalam mengupas bahaya dan ancaman terhadap peradaban politik modern Fukuyama dikritik sangat bias dengan perspektif demokrasi liberal, khususnya AS yang menjadi titik tolak keprihatinannya, tetapi sejumlah argumen pokok dalam buku ini terutama menyangkut penguatan politik identitas dalam spektrum politik populis (kanan) juga menjadi tantangan serius bagi banyak negara demokrasi lainnya, termasuk Indonesia.
Israr Iskandar, dosen sejarah FIB Universitas Andalas
*Pernah dipublikasikan di Singgalang Minggu, 28 Juni 2020


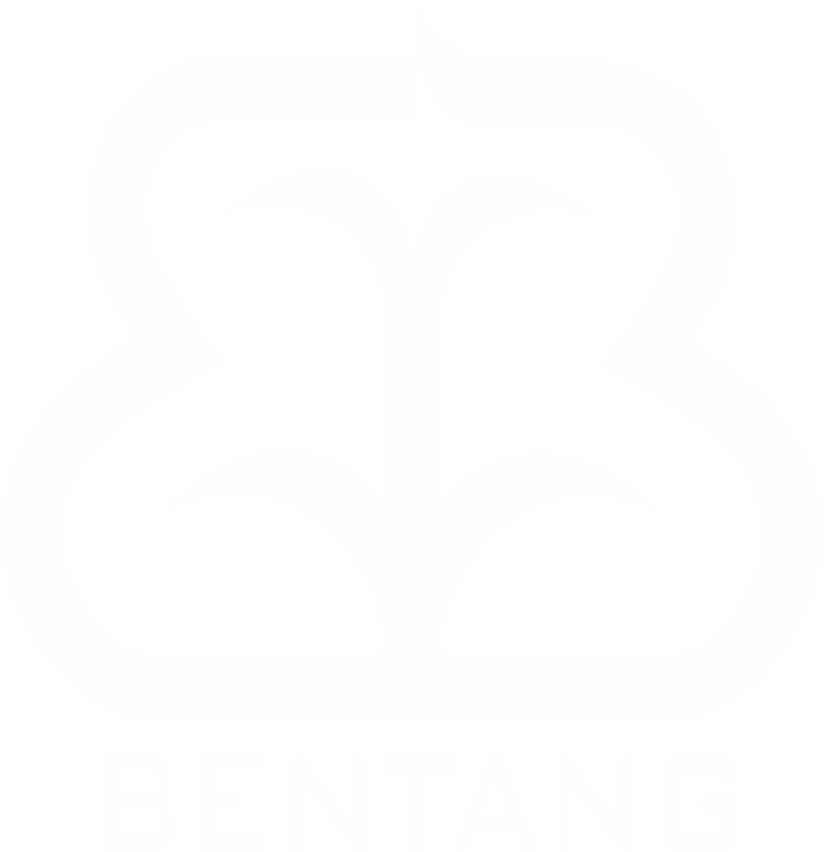






Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!