Sejarah Tionghoa Muslim di Indonesia
Secara garis besar, sejarah Tionghoa Muslim di Indonesia dapat dikelompokkan dalam lima periode. Dalam setiap periode menunjukkan transformasi kaum Tionghoa Muslim. Sejarah Tionghoa Muslim di Indonesia bisa ditarik dari periode budaya hibrida Tionghoa-Jawa Muslim pada abad ke-15 dan 16 hingga kemerosotannya selama periode kolonial Belanda. Kemudian periode pengorganisasian perkumpulan-perkumpulan Tionghoa Muslim selama periode awal kemerdekaan hingga penghapusan segala sesuatu yang berbau Tionghoa di bawah rezim Orde Baru. Serta yang paling belakangan adalah kemunculan ekspresi budaya Tionghoa Muslim di Indonesia pasca 1999.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Tionghoa Muslim dan keterlibatan mereka dalam penyebaran Islam di Jawa sudah ada sejak awal abad ke-15. Sejarawan Lombard dan Salmon (2001) mengungkapkan interaksi antara orang-orang Tionghoa dan budaya lokal pada saat itu digambarkan dalam gaya arsitektur masjid. Dengan menyebutnya sebagai “subkultural Muslim Peranakan”, mereka melihat interaksi tersebut sebagai bentuk “persekutuan suci” kosmopolitan, yang mengombinasikan antara peran-peran positif teologi Islam dan teknik-teknik Tionghoa.
Masa Sebelum Kolonialisme
Beberapa peneliti juga mengatakan sebelum masa kolonial Belanda, sudah terdapat etnis Tionghoa di Jawa, dan mereka adalah Muslim. Mereka adalah Cheng Ho dan pengikutnya. Mereka disebut-sebut memegang peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan dari sumber-sumber sejarah lokal seperti Babad Tanah Jawa dan Serat Kanda, Tionghoa Muslim memiliki andil penting dalam berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Beberapa wali di Jawa, Walisongo juga memiliki asal-usul Tionghoa, kendati hal tersebut masih menjadi perdebatan sampai sekarang.
Al Qurtubi (2003) menambahkan bukti lain pengaruh Tionghoa Muslim pada era itu, yakni adanya pengaruh kuat dalam arsitektur di masjid-masjid dan makam-makam tua di Jawa, seperti makam Sunan Giri di Gresik, desain Keraton Cirebon, dan arsitektur Masjid Demak di Jawa Tengah. Di Jakarta, Masjid Angke dan Masjid Kebon Jeruk juga memiliki ornamen Tionghoa di pintu gerbang dan atapnya.
The (2003) mengungkapkan sebelum kedatangan Belanda, sudah banyak orang Tionghoa yang memeluk Islam sebagai cara mereka untuk membaurkan diri ke dalam masyarakat Jawa. Mereka juga mengadopsi nama-nama Jawa agar bisa naik kelas secara sosial dan politik. Juga bukan hal yang luar biasa bagi mereka untuk berasimilasi ke dalam kelompok mayoritas lokal.
Era Kolonialisme Hindia Belanda
Akan tetapi, seiring perkembangan politik yang dibawa kolonialisme Belanda, bentuk budaya antara orang-orang Tionghoa dan Muslim ini mengalami kemunduran. Oleh karena itu, generasi Tionghoa Muslim setelahnya mengalami kesulitan untuk melacaknya lagi. Sebagian besar dari mereka yang telah terasimilasikan dan budaya Tionghoa-Jawa pun mengalami kemunduran. Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut di antaranya adalah meningkatnya kekuasaan rezim kolonial Belanda, perubahan politik di Tiongkok, perkembangan Islam semakin ortodoks, serta meningkatnya kedatangan perempuan-perempuan Tionghoa dan lahirnya nasionalisme di Tionghoa. Hal ini membuat etnis Tionghoa pada masa berikutnya sebagian besar adalah non-Muslim dan dinilai sebagai “orang lain” yang berbahaya dan “orang asing” yang tidak mampu membaur.
Ketika rezim kolonial Belanda berkuasa, kebijakan-kebijakannya semakin memecah belah. Rezim menciptakan batas-batas yang lebih tegas antara orang Tionghoa dan penduduk asli. Dampaknya, semakin kecil jumlah orang Tionghoa yang memeluk Islam. Kebijakan tersebut misalnya adanya pembagian warga dalam tiga kategori rasial, masing-masing memiliki hak hukum dan hak istimewa yang berbeda-beda. Orang-orang Eropa berada di posisi teratas, orang-orang Timur Asing (terutama Tionghoa, Arab, dan India) berada di tengah-tengah, serta orang pribumi berada di strata terbawah.
Status ini kemudian menimbulkan penilaian di kalangan Tionghoa, bahwa status mereka lebih tinggi dari orang pribumi. Karena Islam rata-rata dipeluk oleh penduduk asli Indonesia, banyak orang Tionghoa beranggapan jika mereka memeluk Islam, sama saja dengan merendahkan derajat mereka. Kendati demikian, masih ada beberapa orang Tionghoa yang memeluk Islam yang sebagian besar karena alasan keamanan dan ekonomi.
Perubahan Situasi Politik
Pasca pembantaian massal penduduk Tionghoa oleh Belanda pada 1740, banyak orang Tionghoa kemudian masuk Islam untuk menghindari kemungkinan menjadi korban. Ada juga yang masuk Islam agar diperlakukan sebagai pribumi dan dikenakan pajak lebih rendah. Hal tersebut kemudian membuat Belanda mencegah konversi keagamaan bagi etnis Tionghoa karena menimbulkan kehilangan yang besar bagi pemerintah kolonial.
Kendati terdapat ketegangan-ketegangan tersebut, keputusan memeluk Islam di kalangan Tionghoa tidak berhenti. Bahkan, beberapa dari mereka ikut terlibat dalam berbagai gerakan anti kolonial dan keagamaan di tingkat lokal. Pada awal 1930-an, ada kegiatan penyebaran Islam yang meningkat oleh Tionghoa Muslim kepada Tionghoa non-Muslim untuk masuk Islam. Bahkan di Sulawesi, Ong Kie Ho mendirikan Partai Islam yang membuatnya kemudian diasingkan ke Jawa pada 1932.
Meski demikian, pergerakan tidak berhenti. Pada 1933, didirikan Partai Tionghoa Islam Indonesia (PTII), tujuannya untuk mengangkat status etnis Tionghoa dengan cara masuk Islam. Di Medan, bersama beberapa pengikutnya Yap A Siong atau Haji Abdussomad mendirikan Persatuan Islam Tionghoa (PIT) pada 1936. Mereka berusaha mewujudkan keislaman dan identitas ketionghoaan mereka secara bersamaan.
Pasca kemerdekaan, PIT yang saat itu dipimpin Abdul Karim Oei Tjeng Hien pindah ke Jakarta dan menggabungkan diri dengan perkumpulan Tionghoa Muslim yang berbasis di Bengkulu. Mereka bergabung dan mendeklarasikan diri menjadi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) pada 1961. Namun karena situasi politik pasca 1965, PITI kemudian menghapuskan identitas Tionghoa di namanya.
Masa Orde Baru
Soeharto secara sistematis melarang semua bentuk ekspresi identitas etnis, budaya, dan keagamaan Tionghoa. Pada waktu bersamaan dia meminggirkan etnis Tionghoa dalam arena-arena sosial, pendidikan, dan politik. PITI mengubah namanya menjadi Pembina Iman Tauhid Islam. Tidak hanya harus mengubah namanya, Soeharto juga memasukkan orang-orang militer di jajaran petinggi PITI.
Bisa dikatakan, masa Orde Baru merupakan periode gelap dalam sejarah PITI. Angin segar bagi PITI baru berembus pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Pada pertengahan Mei 2000, di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang terkenal sangat plural, PITI diperbolehkan menggunakan kata Tionghoa lagi sebagai namanya. Sejak saat itu, orang-orang Tionghoa Muslim bisa lebih leluasa dalam menjalankan ibadah maupun budaya mereka. Mereka juga menghidupkan kembali sejarah dan merawat ikatan mereka dengan umat Muslim di Tiongkok.
Ketahui lebih banyak mengenai Berislam ala Tionghoa, Pergulatan Etnisitas dan Religiositas di Indonesia, karya terbaru Hew Wai Weng. Dapatkan info tentang buku tersebut di sini.
Kontributor: Widi Hermawan
Sumber gambar: Kumparan






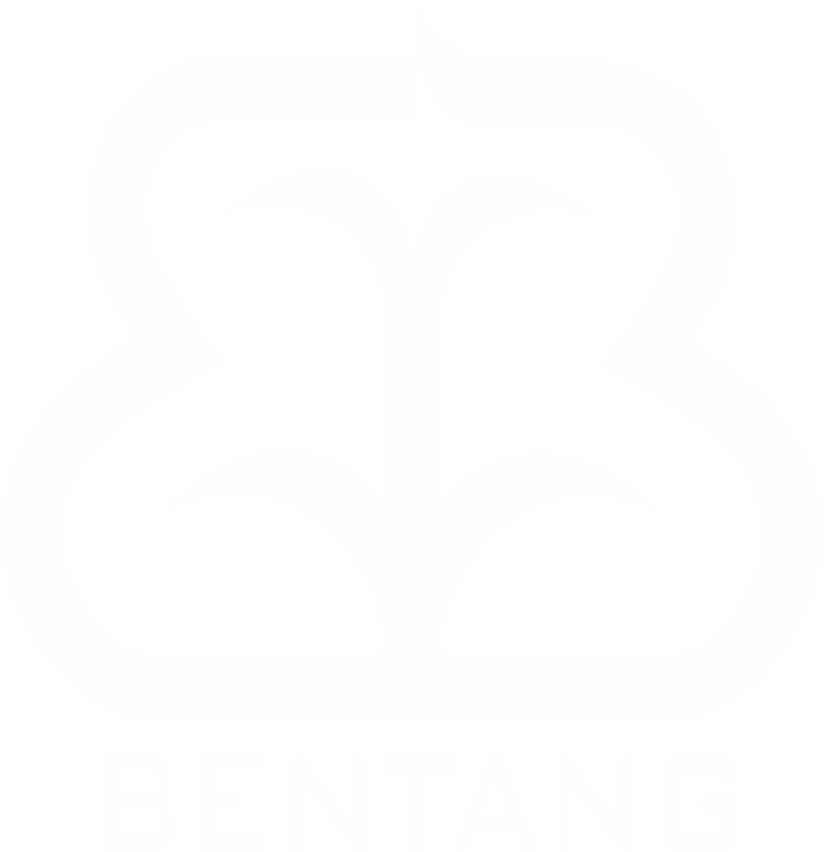






Trackbacks & Pingbacks
[…] Wai Weng dalam bukunya Berislam ala Tionghoa mengungkapkan pembagian kasta-kasta tersebut memunculkan stigma di kalangan etnis Tionghoa kalau […]
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!