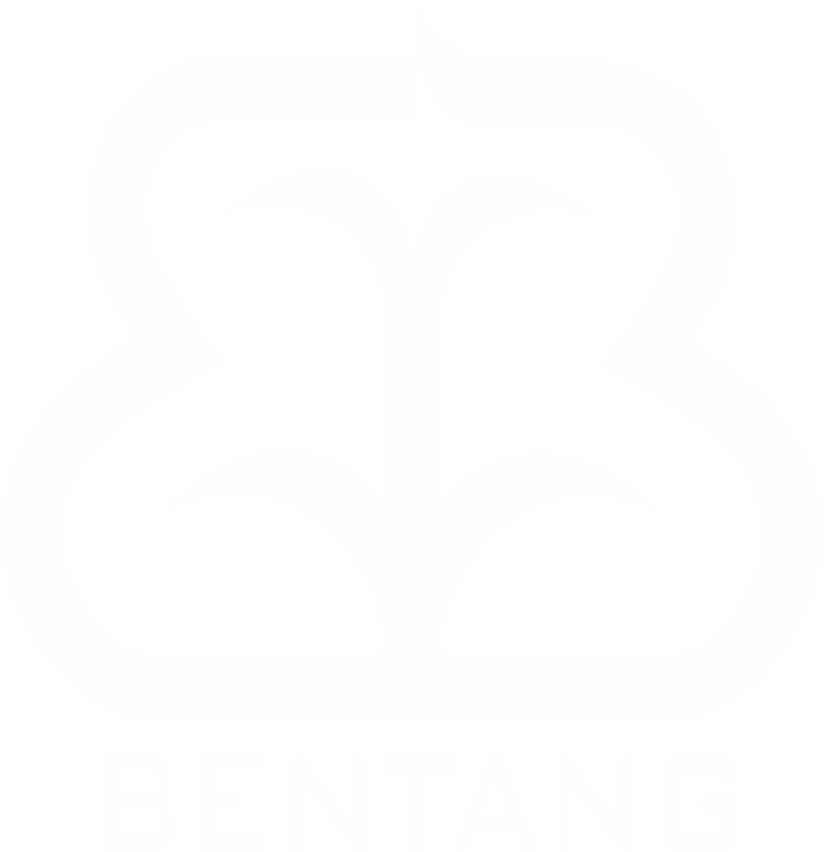Tag Archive for: Sejarah
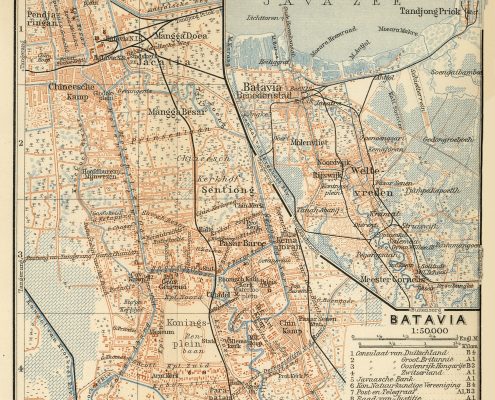
Sejarah Kota-kota di Nusantara pada Abad ke-17
/
0 Comments
Tinggal di kota tertentu dalam jangka waktu cukup lama belum…

Untuk Kamu yang Masih Takut Membuka Masa Lalu
Apakah kamu takut membuka masa lalu? Diskusi tentang masa lalu…
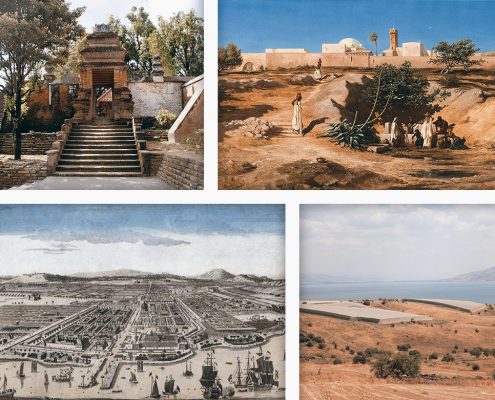
Beragam Latar Tempat dalam Al-Masih: Putra Sang Perawan
Penulis yang melahirkan kesuksesan melalui tetralogi serial novel…

Al Masih: Putra Sang Perawan Karya Terbaru Tasaro GK
Setelah sukses dengan serial novel Muhammad, sang penulis Tasaro…
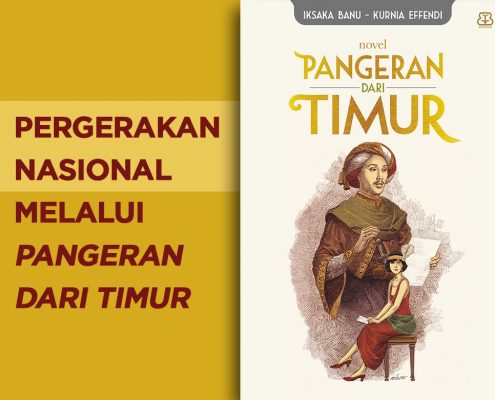
Pergerakan Nasional Melalui Pangeran dari Timur
Pangeran dari Timur merupakan novel karya Iksaka Banu dan Kurnia…
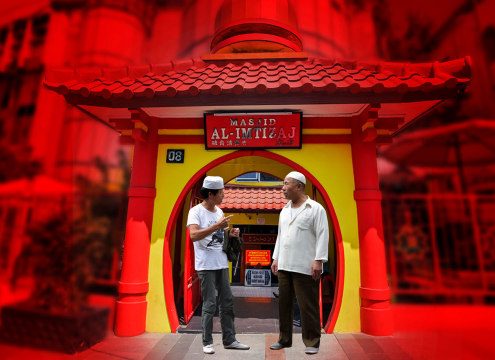
Misteri Lukisan Penangkapan Pangeran Diponegoro Oleh Raden Saleh
Raden Saleh dalam Pangeran Dari Timur
Raden Saleh Syarief Bustaman…

Pangeran Dari Timur : Representasi Maestro Seni Lukis Raden Saleh
Raden Saleh dikenal sebagai pelopor seni lukis modern Indonesia.…
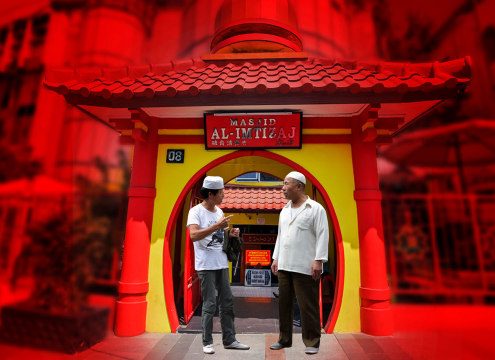
Sejarah Tionghoa Muslim di Indonesia
Secara garis besar, sejarah Tionghoa Muslim di Indonesia dapat…
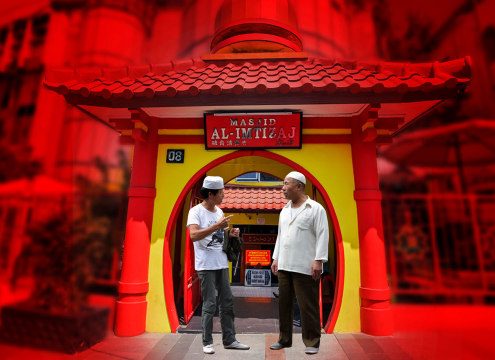
Bukti Keberadaan Kerajaan Majapahit: Ada atau Hanya Legenda?
Bukti Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar…