Tag Archive for: Francis Fukuyama
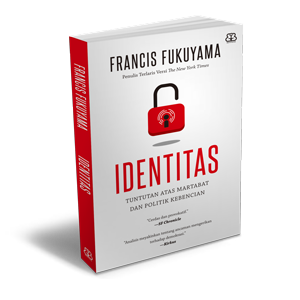
Politik Identitas dan Demokrasi Liberal
/
0 Comments
Francis Fukuyama, ahli ekonomi politik yang fenomenal lewat buku…
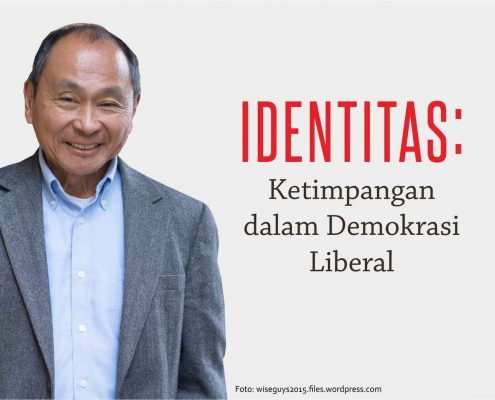
Petaka Amerika dan Ironi Demokrasi
Kita tak melupa Mark Twain. Pengarang bercerita manusia-manusia…
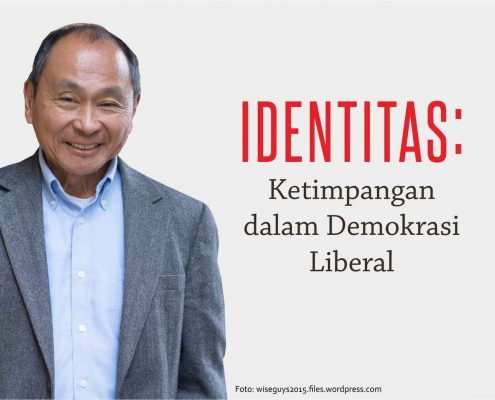
Ketimpangan dalam Demokrasi Liberal
Dalam demokrasi liberal modern, prinsip kedua, kesetaraan, jarang…
