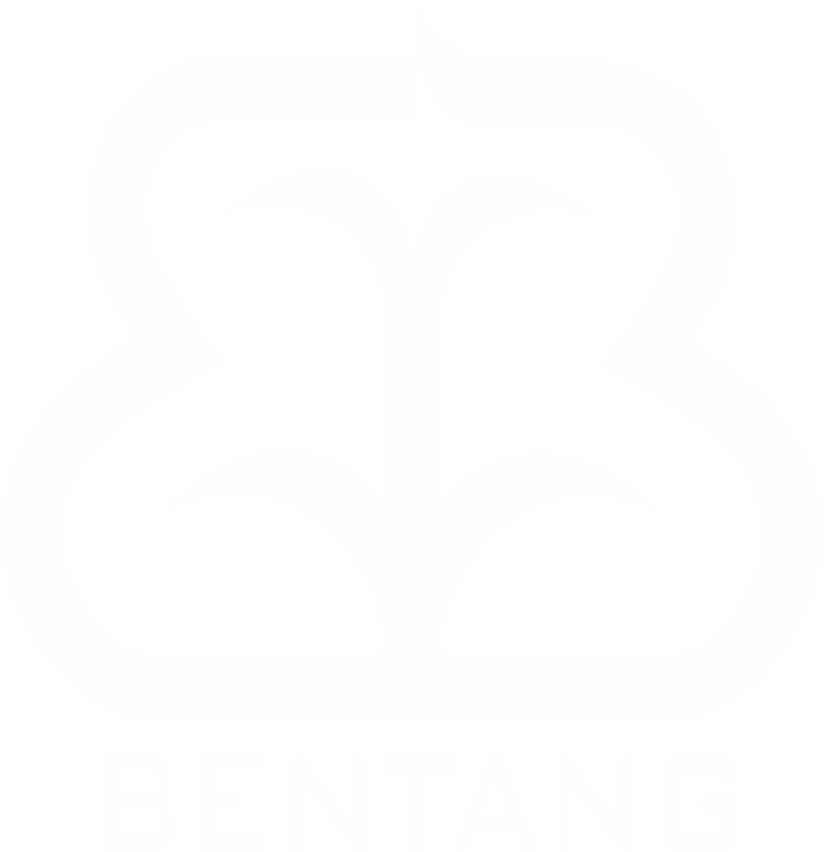Tag Archive for: Tionghoa Muslim
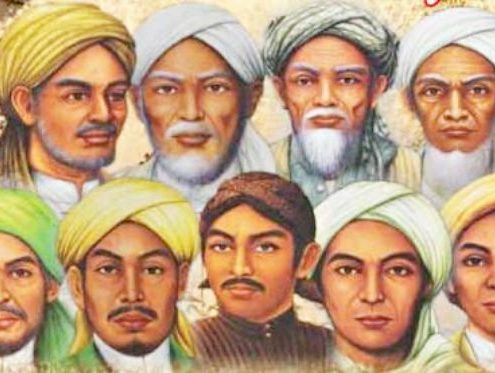
Sebagian Walisongo Keturunan Tionghoa?
/
14 Comments
Sejarah terkait beberapa Walisongo adalah keturunan Tionghoa…
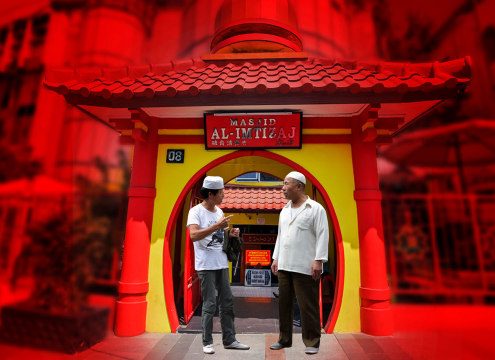
Sejarah Tionghoa Muslim di Indonesia
Secara garis besar, sejarah Tionghoa Muslim di Indonesia dapat…

Eksistensi Tionghoa Muslim Indonesia Masa Belanda
Eksistensi Tionghoa Muslim di Indonesia mengalami pasang surut…

Apa Itu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI)?
Pada 14 April 1961, umat Tionghoa Muslim di Indonesia mendirikan…

Tokoh Tionghoa Muslim di Indonesia
Pasca-Reformasi merupakan angin segar bagi perkembangan komunitas…