Pancasila di Mata Seorang Warga Tionghoa
Bagi saya pribadi, pandangan Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Tionghoa terhadap bangsa ini adalah sesuatu yang istimewa. Sejak kecil, saya bergaul dengan berbagai orang termasuk WNI keturunan Tionghoa. Namun, saya jarang sekali mendapati diskusi dan dialektika yang begitu syahdu dengan mereka terkait dengan situasi dan kondisi Indonesia, baik menyangkut aspek ekonomi, politik, pendidikan, budaya, dan sebagainya.
Salah seorang tokoh keturunan Tionghoa yang begitu terkenal adalah Tionghoa adalah Soe Hok Gie. Walaupun ditakdirkan mati muda, namun kehadirannya masih terasa hingga kini. Dengan semangat juangnya yang tinggi dan sikap kritis yang dimilikinya, ia menjadi seorang aktivis yang begitu disegani – hingga kini. Namun, di zaman seperti ini, apakah masih ada sosok seperti Soe Hok Gie? Salah seorang WNI Tionghoa bernama Audrey Yu Jia Hui adalah salah satu dari sekian banyak orang keturunan Tionghoa yang sangat peduli dengan Indonesia. Ia menulis sebuah surat cinta dalam bukunya Mencari Sila Kelima.
Selama ini, WNI keturunan tionghoa memiliki bahwa mereka bersikap tidak acuh dengan kondisi bangsa ini. Menanggapi sikap tidak acuh tersebut kita tidak boleh lantas menyalahkan mereka. Sebab, sebagian ketidakacuhan itu sendiri disebabkan oleh bangsa kita sendiri. Berbagai diskriminasi dilimpahkan kepada mereka karena mereka adalah keturunan tionghoa. Entah apa yang menjadi dasar bagi negara ini, namun pada saat Soeharto menjabat sebagai presiden, seluruh WNI keturunan Tionghoa dilarang menggunakan nama Cina mereka
Identitas mereka sebagai warga keturunan Tionghoa dicerabut dan dipaksa menjadi Indonesianis dengan simbol-simbol “nama asli” Indonesia. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 5 Keputusan Presiden No. 240 Tahun 1967 tentang Kebijaksanaan Jang Menjangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing (“Keppres 240/1967”) yang menyebutkan:
“Khusus terhadap warga negara Indonesia keturunan asing jang masih memakai nama Cina diandjurkan mengganti nama-namanja dengan nama Indonesia sesuai dengan ketentuan jang berlaku.”
Keluarnya peraturan tersebut kemudian menyebabkan berbondong-bondongnya WNI Tionghoa untuk mengurus nama mereka yang sebelumnya “Liem Yo Giek” menjadi “Budiono”. Perlu kita ketahui pula bahwa klausul peraturan diatas menggunakan kata “dianjurkan”. Kita tahu bahwa anjuran berbeda dengan kewajiban. Namun, implementasi dari peraturan tersebut menjadi sebuah “pelarangan menggunakan nama Cina”. Kini, tak satupun kita dapati WNI Tionghoa yang masih menggunakan nama Cina-nya.
Padahal, jika kita berbicara mengenai konteks “keterasingan”, nama-nama “Abdul”, “Ahmad” dan “Aisyah” adalah nama-nama Arab. Tetapi tidak ada pelarangan terhadap nama-nama tersebut. Nama-nama lain seperti Robert, Alexander, dan sebagainya yang merujuk pada nama-nama “khas” Eropa juga tidak dianjurkan untuk berganti nama. Sebuah film pendek berjudul “Sugiharti Halim” yang dibesut oleh Ariani Darmawan mengisahkan bagaimana nama menjadi sesuatu hal yang sangat penting karena menunjukkan identitas. Kita tahu bahwa dalam hidup ini, identitas adalah ihwal penting.
Dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, kita seringkali membangun sekat yang tebal dengan WNI keturunan Tionghoa. WNI keturunan Tionghoa seolah-olah dipisahkan dari identitas mereka terhadap Indonesia. Mereka dipaksa menggunakan “nama Indonesia” tetapi keberadaannya tidak mendapat perhatian. WNI Tionghoa pun (secara stereotipe) menjadi elitis, membentuk komunal dan lingkaran relasi mereka sendiri. Mereka tidak berbaur dengan masyarakat lain dan berkelompok dengan diri mereka sendiri.
Hal ini adalah salah satu hal yang tidak disukai oleh Audrey yang kini berdomisili di Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Dalam bukunya, “Mencari Sila Kelima”, Audrey menegaskan bahwa dirinya tidak akan hidup hanya untuk mencari uang dan menjadi sosialita bersuami kaya yang doyan mempercantik diri (dalam pengantar yang ditulis oleh J. Sumardianta).
Audrey adalah WNI Tionghoa yang begitu mencintai Pancasila, konsep dasar negara Indonesia. Menurut Audrey, kelima butir Pancasila memiliki makna yang dalam dan sebetulnya mampu membangun rasa persatuan dan kesatuan. Sayangnya, Audrey belum menemukan implementasi dari pancasila itu sendiri.
Alih-alih dipraktikan, Pancasila hanya dihapal untuk ulangan di sekolah. Kelima butir dasar negara tersebut hanya menjadi formalitas dan sekadar atribut negara semata. Padahal, Audrey begitu mengagumi pancasila dan ia percaya, praktik berpancasila yang baik akan menghadilkan sikap yang baik.
Dalam bukunya, Mencari Sila Kelima, Audrey memang mengkritik luputnya penerapan pancasila. Ia kemudian mengambil beberapa filsafat kuno Tiongkok yang selaras dengan Pancasila. Dengan menganalogikan filsafat kuno Tiongkok tersebut, Audrey mengkritisi berbagai persoalan yang saat ini terjadi di Indonesia seperti pendidikan, praktik kehidupan beragama, dan lain sebagainya. Bagi Audrey sendiri, kunci dari kehidupan harmonis adalah kesediaan untuk mengasihi sesama. Sebelumnya Audrey pernah menulis tentang pergulatannya mencintai Indonesia — yang berujung pada rasa patah hati. Ia menulsikan semua pandangannya tentang Indonesia dengan sangat jujur dalam bukunya “Mellow Yellow Drama”.
Apa yang ingin Audrey tuntut dalam pelaksanaan Pancasila adalah kembalinya fungsi pendidikan dan agama untuk mengasihi sesama. Bukannya menjadi alat untuk membuat kelas-kelas di masyarakat, merasa hebat, menindas orang lain, dan menakut-nakuti sesama. Sangat besar harapan Audrey untuk mewujudukan implementasi butir-butir Pancasila. Baginya, pancasila akan menjadi dasar untuk mencintai sesama dan negara. Audrey sebagai WNI Tionghoa yang “teracuhkan” memiliki berbagai gagasan dalam bukunya; bagaimana cara ia memandang pancasila. Dan bagaimana cara ia memandang Indonesia. Audrey mungkin bukan Gie, tetapi dia juga memiliki gagasan yang besar kepada Indonesia.
Oleh : Lamia Putri D. Bagi saya pribadi, pandangan Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Tionghoa terhadap bangsa ini adalah sesuatu yang istimewa. Sejak kecil, saya bergaul dengan berbagai orang termasuk WNI keturunan Tionghoa. Namun, saya jarang sekali mendapati diskusi dan dialektika yang begitu syahdu dengan mereka terkait dengan situasi dan kondisi Indonesia, baik menyangkut aspek ekonomi, politik, pendidikan, budaya, dan sebagainya.
Salah seorang tokoh keturunan Tionghoa yang begitu terkenal adalah Tionghoa adalah Soe Hok Gie. Walaupun ditakdirkan mati muda, namun kehadirannya masih terasa hingga kini. Dengan semangat juangnya yang tinggi dan sikap kritis yang dimilikinya, ia menjadi seorang aktivis yang begitu disegani – hingga kini. Namun, di zaman seperti ini, apakah masih ada sosok seperti Soe Hok Gie? Salah seorang WNI Tionghoa bernama Audrey Yu Jia Hui adalah salah satu dari sekian banyak orang keturunan Tionghoa yang sangat peduli dengan Indonesia. Ia menulis sebuah surat cinta dalam bukunya Mencari Sila Kelima.
Selama ini, WNI keturunan tionghoa memiliki bahwa mereka bersikap tidak acuh dengan kondisi bangsa ini. Menanggapi sikap tidak acuh tersebut kita tidak boleh lantas menyalahkan mereka. Sebab, sebagian ketidakacuhan itu sendiri disebabkan oleh bangsa kita sendiri. Berbagai diskriminasi dilimpahkan kepada mereka karena mereka adalah keturunan tionghoa. Entah apa yang menjadi dasar bagi negara ini, namun pada saat Soeharto menjabat sebagai presiden, seluruh WNI keturunan Tionghoa dilarang menggunakan nama Cina mereka
Identitas mereka sebagai warga keturunan Tionghoa dicerabut dan dipaksa menjadi Indonesianis dengan simbol-simbol “nama asli” Indonesia. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 5 Keputusan Presiden No. 240 Tahun 1967 tentang Kebijaksanaan Jang Menjangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing (“Keppres 240/1967”) yang menyebutkan:
“Khusus terhadap warga negara Indonesia keturunan asing jang masih memakai nama Cina diandjurkan mengganti nama-namanja dengan nama Indonesia sesuai dengan ketentuan jang berlaku.”
Keluarnya peraturan tersebut kemudian menyebabkan berbondong-bondongnya WNI Tionghoa untuk mengurus nama mereka yang sebelumnya “Liem Yo Giek” menjadi “Budiono”. Perlu kita ketahui pula bahwa klausul peraturan diatas menggunakan kata “dianjurkan”. Kita tahu bahwa anjuran berbeda dengan kewajiban. Namun, implementasi dari peraturan tersebut menjadi sebuah “pelarangan menggunakan nama Cina”. Kini, tak satupun kita dapati WNI Tionghoa yang masih menggunakan nama Cina-nya.
Padahal, jika kita berbicara mengenai konteks “keterasingan”, nama-nama “Abdul”, “Ahmad” dan “Aisyah” adalah nama-nama Arab. Tetapi tidak ada pelarangan terhadap nama-nama tersebut. Nama-nama lain seperti Robert, Alexander, dan sebagainya yang merujuk pada nama-nama “khas” Eropa juga tidak dianjurkan untuk berganti nama. Sebuah film pendek berjudul “Sugiharti Halim” yang dibesut oleh Ariani Darmawan mengisahkan bagaimana nama menjadi sesuatu hal yang sangat penting karena menunjukkan identitas. Kita tahu bahwa dalam hidup ini, identitas adalah ihwal penting.
Dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, kita seringkali membangun sekat yang tebal dengan WNI keturunan Tionghoa. WNI keturunan Tionghoa seolah-olah dipisahkan dari identitas mereka terhadap Indonesia. Mereka dipaksa menggunakan “nama Indonesia” tetapi keberadaannya tidak mendapat perhatian. WNI Tionghoa pun (secara stereotipe) menjadi elitis, membentuk komunal dan lingkaran relasi mereka sendiri. Mereka tidak berbaur dengan masyarakat lain dan berkelompok dengan diri mereka sendiri.
Hal ini adalah salah satu hal yang tidak disukai oleh Audrey yang kini berdomisili di Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Dalam bukunya, “Mencari Sila Kelima”, Audrey menegaskan bahwa dirinya tidak akan hidup hanya untuk mencari uang dan menjadi sosialita bersuami kaya yang doyan mempercantik diri (dalam pengantar yang ditulis oleh J. Sumardianta).
Audrey adalah WNI Tionghoa yang begitu mencintai Pancasila, konsep dasar negara Indonesia. Menurut Audrey, kelima butir Pancasila memiliki makna yang dalam dan sebetulnya mampu membangun rasa persatuan dan kesatuan. Sayangnya, Audrey belum menemukan implementasi dari pancasila itu sendiri.
Alih-alih dipraktikan, Pancasila hanya dihapal untuk ulangan di sekolah. Kelima butir dasar negara tersebut hanya menjadi formalitas dan sekadar atribut negara semata. Padahal, Audrey begitu mengagumi pancasila dan ia percaya, praktik berpancasila yang baik akan menghadilkan sikap yang baik.
Dalam bukunya, Mencari Sila Kelima, Audrey memang mengkritik luputnya penerapan pancasila. Ia kemudian mengambil beberapa filsafat kuno Tiongkok yang selaras dengan Pancasila. Dengan menganalogikan filsafat kuno Tiongkok tersebut, Audrey mengkritisi berbagai persoalan yang saat ini terjadi di Indonesia seperti pendidikan, praktik kehidupan beragama, dan lain sebagainya. Bagi Audrey sendiri, kunci dari kehidupan harmonis adalah kesediaan untuk mengasihi sesama. Sebelumnya Audrey pernah menulis tentang pergulatannya mencintai Indonesia — yang berujung pada rasa patah hati. Ia menulsikan semua pandangannya tentang Indonesia dengan sangat jujur dalam bukunya “Mellow Yellow Drama”.
Apa yang ingin Audrey tuntut dalam pelaksanaan Pancasila adalah kembalinya fungsi pendidikan dan agama untuk mengasihi sesama. Bukannya menjadi alat untuk membuat kelas-kelas di masyarakat, merasa hebat, menindas orang lain, dan menakut-nakuti sesama. Sangat besar harapan Audrey untuk mewujudukan implementasi butir-butir Pancasila. Baginya, pancasila akan menjadi dasar untuk mencintai sesama dan negara. Audrey sebagai WNI Tionghoa yang “teracuhkan” memiliki berbagai gagasan dalam bukunya; bagaimana cara ia memandang pancasila. Dan bagaimana cara ia memandang Indonesia. Audrey mungkin bukan Gie, tetapi dia juga memiliki gagasan yang besar kepada Indonesia.
Oleh : Lamia Putri D.bentang



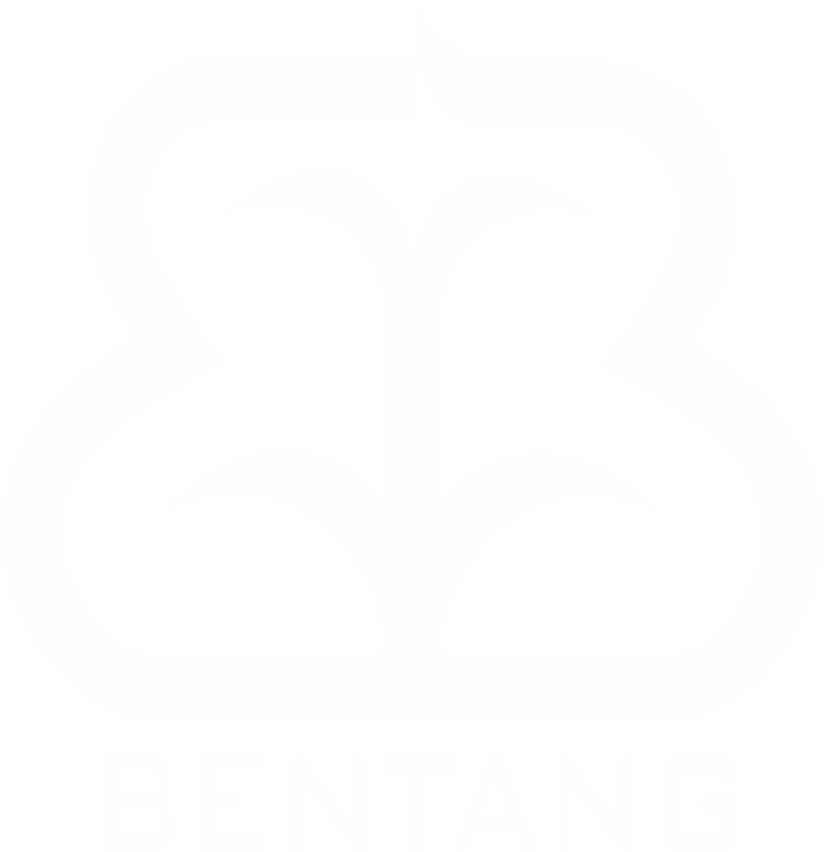






Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!