Hoaks Bikin Muak
Jalaluddin Rakhmat, pakar ilmu komunikasi, mengatakan bahwa 70 persen waktu bangun kita digunakan untuk berkomunikasi. Bahkan, kita belajar menjadi manusia melalui komunikasi. Komunikasi menjadi menjadi penting untuk pertumbuhan pribadi kita. Melalui komunikasi, kita menemukan diri kita, mengembangkan konsep diri, dan menetapkan hubungan kita dengan dunia di sekitar kita.
Komunikasi—secara lisan atau melalui media, utamanya media sosial (medsos)—juga ditujukan untuk menumbuhkan hubungan sosial yang baik. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak tahan hidup sendiri. Kita ingin berhubungan dengan orang lain secara positif. Komunikasi positif bisa menciptakan suasana yang harmonis, bahkan bisa mendamaikan dua pihak yang bertikai. Namun sebaliknya, komunikasi negatif bisa juga menyulut pertentangan dan permusuhan.
Disadari atau tidak, akhir-akhir ini komunikasi negatif itu marak terjadi karena penyalahgunaan fungsi medsos sebagai media informasi, penampung aspirasi, dan hiburan. Oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab memanfaatkannya untuk memantik kebencian dan menyebar informasi palsu, fitnah, dan adu domba antar warganet. Semuanya itu tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan sama sekali. Padahal bangsa kita punya akhlakul karimah yang merupakan alasan utama diutusnya Rasulullah Muhammad, “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” Lebih-lebih jika penyalahgunaan fungsi medsos itu juga menyangkut ajaran dan perilaku keagamaan.
Salah satu poin penting yang kemukakan oleh penulis bahwa diskusi kita di medsos sama riuh dan berisiknya seperti di pasar. Gayanya saja kita pakai smartphone saat diskusi, padahal nyatanya masih berupa kerumunan yang saling berteriak dan memunculkan mekanisme pertahanan diri. Kita pun cenderung memercayai sesuatu yang memang ingin kita percayai. Demikian pula dengan share atau forward di medsos yang lebih kepada unsur like or dislike daripada benar atau tidaknya berita tersebut. Jadi, yang menentukan itu bukan benar atau tidaknya isi berita, melainkan apakah kita senang atau benci dengan tokoh yang dibicarakan.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa jika ada postingan dari kiai atau guru besar yang keilmuan keagamaannya tidak diragukan lagi, banyak sekali yang bertanya tentang ada dalil atau referensinya atau tidak, ada di kitab apa, atau hadistnya shahih atau tidak. Sedangkan jika menyebar berita hoaks, tak bertanya lagi tentang dalil-dalil dan lain sebagainya, dan langsung share. Maka, postingan agama yang mengajarkan kebaikan-kebaikan menjadi kalah cepat dengan postingan yang menghembuskan kebencian.
Perdebatan sengit di medsos juga dipicu dengan postingan dengan embel-embel hadits tanpa disertai penjelasan yang semestinya. Seperti larangan Nabi untuk duduk dengan memeluk lutut, tentang duduk yang dimurkai (duduk dengan salah satu tangan menjadi tumpuan), atau duduk iq’a seperti iq’a-nya anjing. Padahal, larangan Nabi tidak mesti bermakna haram, melainkan makruh saja. Atau tidak semua larangan Nabi masuk pada bab hukum, tetapi menyangkut etika dan adab. Dan teks hadits harus dipahami dari sisi konteksnya sebagai salah satu asbabul wurud (sebab-sebab hadits disabdakan oleh Nabi).
Demikian pula dengan bacaan-bacaan (doa-doa) yang sering di-bid’ah-kan oleh sekelompok umat Islam, seperti doa saat duduk di antara dua sujud. Di medsos, digembar-gemborkan bahwa menambah kata wa’fu ‘anni dalam doa di antara dua sujud itu adalah bikinan ulama Indonesia yang tidak ada dasar dalilnya. Padahal, jika dilacak, kata tersebut terdapat dalam kitab-kitab para ulama Timur Tengah dan sekitarnya. Dan lagi, dalam kitab-kitab tersebut diriwayatkan pula doa-doa lain seperti doa sapu jagat. Jadi, jangankan ditambah dengan doa-doa lain yang diperbolehkan, bahkan tidak membaca doa yang dipermasalahkan itu pun salatnya sudah sah. Begitu pun dengan doa berbuka puasa, macam-macam doa dalam salat, dan doa-doa lainnya, yang perdebatannya tidak kalah sengit.
Dan ditengarai bahwa keriuhan di medsos juga dipicu oleh pertanyaan yang diajukan bukan murni untuk bertanya atau untuk benar-benar ingin mengetahui jawaban. Maksudnya, adakalanya orang bertanya untuk menunjukkan bahwa yang bertanya itu lebih tahu dari yang ditanya. Atau bertanya dengan maksud untuk berdebat, menyindir, mem-bully, atau tebar pesona kepada para warganet.
Akhirnya, setelah kita mafhum dari buku ini, masihkah kita hobi untuk memperdebatkan hal-hal yang sekunder, yang pada akhirnya mereka saling menyalahkan, bahkan sampai mengkafirkan sesama mukmin dan muslim? “Istafti qalbak”, tanyalah hati nuranimu, Kawan! (*)
Moh. Mahrus Hasan, pembina ekskul KIR-literasi “Sabha Pena” dan pembina Majalah Pendidikan “Al-Mashalih” MAN Bondowoso
*Pernah dipublikasikan di koran Baratha Post







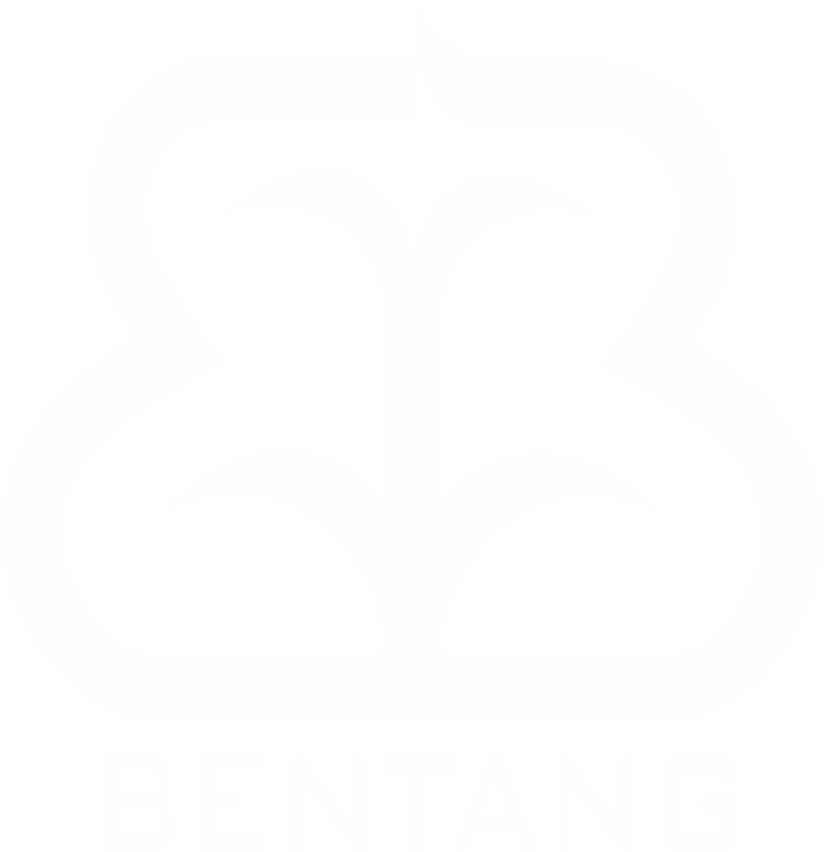







Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!