Petualangan Bahasa Indonesia
Sudah jamak dipahami bahwa Bahasa Indonesia yang berkembang dewasa ini adalah produk bahasa yang diturunkan dari bahasa Melayu. Sebagian besar ahli bahasa arus utama (mainstream) umumnya menyebutkan bahwa cikal bakal bahasa persatuan itu adalah bahasa Melayu tinggi, yang diadaptasi oleh Belanda melalui pendirian balai bacaan rakyat, Balai Pustaka, pada 1917.
Konon, awalnya, bahasa melayu dengan “kadar” tinggi ini hanya dipakai dalam kalangan istana, bangsawan, dan kaum terpelajar lainnya secara terbatas pada abad ke-15, yaitu pada masa keemasan kesultanan Malaka, dan kemudian digunakan di wilayah kesultanan Riau-Johor. Sementara itu, sebagian minoritas sejarahwan bahasa kontemporer menggugat penggunaan Melayu tinggi sebagai fondasi bahasa Indonesia sebagai tindakan politis, sistematis dan terstruktur untuk menghilangkan peran bahasa melayu rendah yang pada waktu itu bergerak cepat dengan sirkulasi yang menjangkau pembaca dalam jumlah besar, serta sebagian di antaranya membangkitkan nasionalisme melawan pemerintah kolonial Belanda. Pendapat terakhir ini setidaknya pernah diangkat dalam sebuah diskusi bertajuk Tionghoa dan Subversi Sastra Melayu Rendah pada 2008 dengan menghadirkan beberapa pakar sejarah bahasa di antaranya Ajip Rosidi dan Jakob Sumardjo (Rukardi, 2008, Oktober 31).
Yang menarik, penulis Sastra Nasionalisme Pasca Kolonialitas, Katrin Bandel (2013, hlm. 41-45) menolak anggapan bahwa naskah melayu rendah berisi hal-hal yang membangkitkan semangat kebangsaan, karena tidak terbukti pada kebanyakan naskah yang ditelitinya, meskipun, seperti yang ditunjukkan Jacob Sumardjo, mengutip Claudine Salmon, penulis Literature in Malay by The Chinese of Indonesia, ada sekira 3005 karya tulis yang menggunakan bahasa melayu rendah sampai tahun 1942 yang ditulis oleh 806 penulis. Pandangan Katrin ini sejalan dengan pendapat Ajip Rosidi bahwa produk berbahasa melayu-pasar lebih berorientasi pasar dan hiburan dibandingkan menyulut api nasionalisme. Namun diskusi tentang sastra Melayu-Tionghoa tampaknya tidak akan lekas selesai, sebab menurut Irwansyah (2010), dalam Sastra Melayu-Tionghoa dan Nasionalisme, karena “sastra Melayu-Tionghoa atau sastra Indonesia-Tionghoa adalah sastra kaum minoritas.” posisinya dalam dunia sastra Indonesia tampak diabaikan. Cap yang sering dikaitkan di antaranya adalah karya sastra yang liar karena diterbitkan secara swasta, dan cabul.
Sejauh yang dapat ditelusuri konon penggunaan Melayu rendah atau Melayu pasar awalnya sebagai sebuah kebutuhan menjembatani ekspresi bahasa kaum peranakan (istilah ini awalnya digunakan untuk menunjuk Muslim Tionghoa yang membentuk kelompok terpisah dengan orang Tionghoa lainnya, namun kemudian diadopsi oleh Belanda sebagai istilah khusus untuk kelahiran Hindia Belanda) yang kebanyakan bergelut dalam bisnis, terlebih pada saat itu umumnya bahasa melayu digunakan oleh banyak etnis mewakili banyak kepentingan seperti pejabat pemerintah, pedagang migran dan kaum eurosia (keturunan eropa dan asia). Akan tetapi, seperti ditulis Suhandinata (2009) dalam WNI keturunan Tionghoa dalam stabilitas ekonomi dan politik Indonesia, setelah perang dunia kedua berakhir dan kemerdekaan Indonesia, bahasa dan sastra melayu-pasar juga ikut punah.
Menilik perkembangannya, Bahasa Melayu telah digunakan sejak kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Beberapa bukti terhadap klaim ini adalah artefak yang ditemukan secara tersebar mulai dari Aceh, Palembang, Bangka Barat dan Jambi. Sebuah prasasti paling tua yang diyakini sebagai sumber bahasa Melayu kuno, misalnya, ditemukan pada Prasasti Kedukan Bukit di Palembang periode 683 Masehi. Jika ditarik lebih jauh lagi, bahasa melayu ini merupakan cabang dari bahasa-bahasa Sunda-Sulawesi yang menginduk kepada keluarga bahasa Austronesia.
Pada awal abad 19 pemerintah Belanda melalui seorang ahli bahasa bernama Van Ophuijsen menyusun sebuah sistem bahasa yang didasarkan pada bahasa melayu tinggi dan memperkenalkan edjaan atas namanya sendiri yang sebagian besar dipengaruhi oleh bahasa latin. Perlahan tapi pasti, bahasa Indonesia semakin berjalan menjauh dari bahasa melayu terutama ketika pada 28 Oktober 1928 sekumpulan pemuda berikrar secara kolektif untuk menggunakan bahasa indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa yang menandakan identitas kebangsaan. Peristiwa yang kemudian kita kenal sebagai “Soempah Pemoeda”.
Tahun 1928 adalah tahun kelahiran Bahasa Indonesia yang meskipun awalnya banyak meminjam dari bahasa melayu namun kini telah menjadi sebuah bahasa yang terus hidup dan berkembang. Lebih jauh dewasa ini kaum muda kreatif yang terbiasa menggunakan gadget dan berkirim pesan mengenalkan banyak kosa kata gaul dan turunan bahasa Alay, dengan mengubah karakter ke dalam angka. Tentu dengan memasukkan hal penting bahwa bahasa Indonesia secara digdaya berlaku untuk banyak kepentingan lainnya termasuk bahasa akademik berupa tulisan hasil penelitian, jurnal ilmiah dan banyak lagi. Sudah sepatutnya kita berbahagia karena mewarisi bahasa yang dapat mempersatukan suku bangsa dari timur sampai ke pulau paling barat. Hal yang tidak dapat dicapai oleh bahasa Hindi, yang digagas Jawaharlal Nehru, yang sempat dicita-citakan menjadi bahasa pemersatu di anak benua India. Sudah jamak dipahami bahwa Bahasa Indonesia yang berkembang dewasa ini adalah produk bahasa yang diturunkan dari bahasa Melayu. Sebagian besar ahli bahasa arus utama (mainstream) umumnya menyebutkan bahwa cikal bakal bahasa persatuan itu adalah bahasa Melayu tinggi, yang diadaptasi oleh Belanda melalui pendirian balai bacaan rakyat, Balai Pustaka, pada 1917.
Konon, awalnya, bahasa melayu dengan “kadar” tinggi ini hanya dipakai dalam kalangan istana, bangsawan, dan kaum terpelajar lainnya secara terbatas pada abad ke-15, yaitu pada masa keemasan kesultanan Malaka, dan kemudian digunakan di wilayah kesultanan Riau-Johor. Sementara itu, sebagian minoritas sejarahwan bahasa kontemporer menggugat penggunaan Melayu tinggi sebagai fondasi bahasa Indonesia sebagai tindakan politis, sistematis dan terstruktur untuk menghilangkan peran bahasa melayu rendah yang pada waktu itu bergerak cepat dengan sirkulasi yang menjangkau pembaca dalam jumlah besar, serta sebagian di antaranya membangkitkan nasionalisme melawan pemerintah kolonial Belanda. Pendapat terakhir ini setidaknya pernah diangkat dalam sebuah diskusi bertajuk Tionghoa dan Subversi Sastra Melayu Rendah pada 2008 dengan menghadirkan beberapa pakar sejarah bahasa di antaranya Ajip Rosidi dan Jakob Sumardjo (Rukardi, 2008, Oktober 31).
Yang menarik, penulis Sastra Nasionalisme Pasca Kolonialitas, Katrin Bandel (2013, hlm. 41-45) menolak anggapan bahwa naskah melayu rendah berisi hal-hal yang membangkitkan semangat kebangsaan, karena tidak terbukti pada kebanyakan naskah yang ditelitinya, meskipun, seperti yang ditunjukkan Jacob Sumardjo, mengutip Claudine Salmon, penulis Literature in Malay by The Chinese of Indonesia, ada sekira 3005 karya tulis yang menggunakan bahasa melayu rendah sampai tahun 1942 yang ditulis oleh 806 penulis. Pandangan Katrin ini sejalan dengan pendapat Ajip Rosidi bahwa produk berbahasa melayu-pasar lebih berorientasi pasar dan hiburan dibandingkan menyulut api nasionalisme. Namun diskusi tentang sastra Melayu-Tionghoa tampaknya tidak akan lekas selesai, sebab menurut Irwansyah (2010), dalam Sastra Melayu-Tionghoa dan Nasionalisme, karena “sastra Melayu-Tionghoa atau sastra Indonesia-Tionghoa adalah sastra kaum minoritas.” posisinya dalam dunia sastra Indonesia tampak diabaikan. Cap yang sering dikaitkan di antaranya adalah karya sastra yang liar karena diterbitkan secara swasta, dan cabul.
Sejauh yang dapat ditelusuri konon penggunaan Melayu rendah atau Melayu pasar awalnya sebagai sebuah kebutuhan menjembatani ekspresi bahasa kaum peranakan (istilah ini awalnya digunakan untuk menunjuk Muslim Tionghoa yang membentuk kelompok terpisah dengan orang Tionghoa lainnya, namun kemudian diadopsi oleh Belanda sebagai istilah khusus untuk kelahiran Hindia Belanda) yang kebanyakan bergelut dalam bisnis, terlebih pada saat itu umumnya bahasa melayu digunakan oleh banyak etnis mewakili banyak kepentingan seperti pejabat pemerintah, pedagang migran dan kaum eurosia (keturunan eropa dan asia). Akan tetapi, seperti ditulis Suhandinata (2009) dalam WNI keturunan Tionghoa dalam stabilitas ekonomi dan politik Indonesia, setelah perang dunia kedua berakhir dan kemerdekaan Indonesia, bahasa dan sastra melayu-pasar juga ikut punah.
Menilik perkembangannya, Bahasa Melayu telah digunakan sejak kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Beberapa bukti terhadap klaim ini adalah artefak yang ditemukan secara tersebar mulai dari Aceh, Palembang, Bangka Barat dan Jambi. Sebuah prasasti paling tua yang diyakini sebagai sumber bahasa Melayu kuno, misalnya, ditemukan pada Prasasti Kedukan Bukit di Palembang periode 683 Masehi. Jika ditarik lebih jauh lagi, bahasa melayu ini merupakan cabang dari bahasa-bahasa Sunda-Sulawesi yang menginduk kepada keluarga bahasa Austronesia.
Pada awal abad 19 pemerintah Belanda melalui seorang ahli bahasa bernama Van Ophuijsen menyusun sebuah sistem bahasa yang didasarkan pada bahasa melayu tinggi dan memperkenalkan edjaan atas namanya sendiri yang sebagian besar dipengaruhi oleh bahasa latin. Perlahan tapi pasti, bahasa Indonesia semakin berjalan menjauh dari bahasa melayu terutama ketika pada 28 Oktober 1928 sekumpulan pemuda berikrar secara kolektif untuk menggunakan bahasa indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa yang menandakan identitas kebangsaan. Peristiwa yang kemudian kita kenal sebagai “Soempah Pemoeda”.
Tahun 1928 adalah tahun kelahiran Bahasa Indonesia yang meskipun awalnya banyak meminjam dari bahasa melayu namun kini telah menjadi sebuah bahasa yang terus hidup dan berkembang. Lebih jauh dewasa ini kaum muda kreatif yang terbiasa menggunakan gadget dan berkirim pesan mengenalkan banyak kosa kata gaul dan turunan bahasa Alay, dengan mengubah karakter ke dalam angka. Tentu dengan memasukkan hal penting bahwa bahasa Indonesia secara digdaya berlaku untuk banyak kepentingan lainnya termasuk bahasa akademik berupa tulisan hasil penelitian, jurnal ilmiah dan banyak lagi. Sudah sepatutnya kita berbahagia karena mewarisi bahasa yang dapat mempersatukan suku bangsa dari timur sampai ke pulau paling barat. Hal yang tidak dapat dicapai oleh bahasa Hindi, yang digagas Jawaharlal Nehru, yang sempat dicita-citakan menjadi bahasa pemersatu di anak benua India.bentang

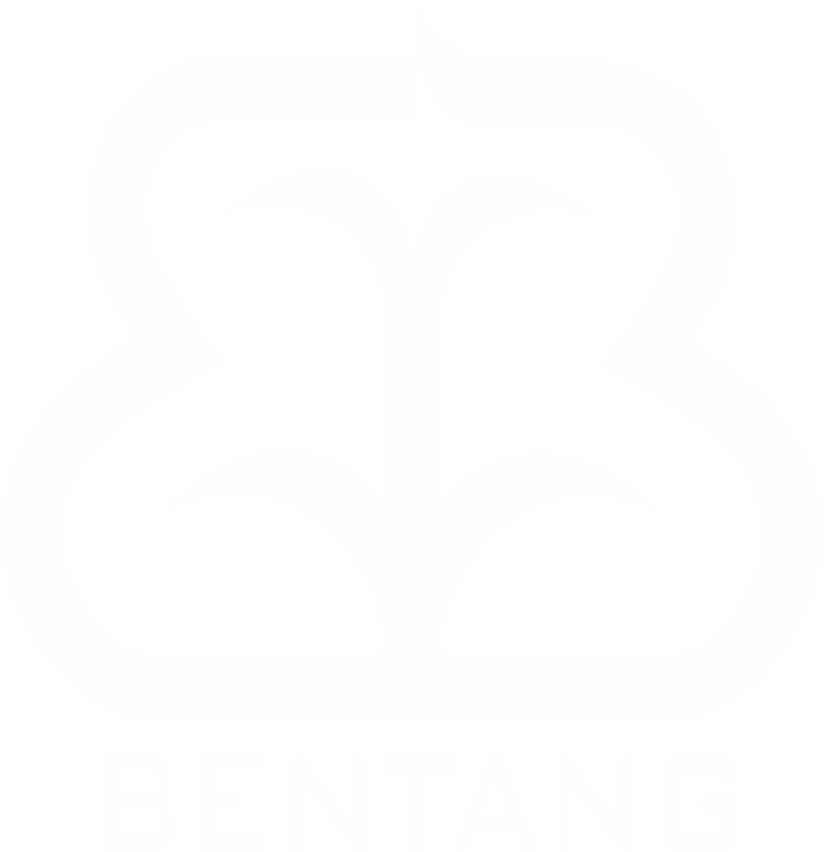





Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!