MELIHAT JERAPAH DARI BALIK JENDELA RUMAH PETER ZILAHY

Pagi itu sebuah surat elektronik mendarat tanpa aba-aba. Saya mengenal pengirimnya cukup baik dari kurun sepuluh tahun lalu atau bahkan lebih. Pertemuan pertama saya ketika itu adalah Festival para penulis di Ubud, 2008. karyanya dalam bahasa Indonesia juga terbit pada tahun yang sama. Boleh dibilang saya membajaknya datang ke Yogyakarta, kemudian Jakarta sekaligus menandai semacam ritual diskusi buku bersama penulis. Peter Zilahy, nama yang tidak mungkin saya lupakan. Caranya membungkus sejarah, autobiografi, dan peristiwa besar di Eropa lainnya dalam sebuah kamus bergambar, akan tetapi juga sebuah novel, luar biasa cerdas. Alih-alih selusinan bab yang membosankan, Zilahy memaparkan kisahnya secara alfabetis berjumlah 44. benar, Anda tidak sedang keliru membaca, jumlah seluruh alfabet dalam bahasa Hungaria adalah 44 bukan 26 seperti yang kita pelajari sejak tadika.
“Hei, Salman. Kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi dengan penerbitan? Bisakah kamu bertahan? Tolong kirim pesan. Aku di New York. Situasinya buruk sekali di sini,”
Surat itu bertitimangsa Senin, 6 April 2020. Sebetulnya datangnya surel itu juga cukup kebetulan karena hari itu masa-masa awal WFH (work from home) dan bacaan saya Senin pagi itu adalah The Last Window Giraffe, sebuah bacaan tidak ringan, berlapis-lapis, tetapi tetap menarik dengan publikasi di 28 negara termasuk Indonesia pada 2008. Dalam beberapa kali korespondensi kami, Peter berusaha mengabarkan situasi chaos yang menimpa banyak penerbit bukunya di sejumlah negara. Dia berbaik hati memberikan semacam sinyal akan terjadi banyak hal buruk sebagai akibat pandemi Corona ini. “Wabah ini akan tampak buruk. Bersiaplah,” pungkas Peter. Tak berapa lama, toko-toko buku tutup. Hampir semua karyawan bekerja dari rumah, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah mikroorganisme tak kasat mata memaksa semua orang bekerja dari balik pintu, anak-anak belajar dari rumah, dengan harap-harap cemas akan situasi esok yang semakin tak pasti.
Pada periode 1947, seorang penulis berkebangsaan Prancis, kelahiran Aljazair, Albert Camus, melahirkan sebuah karya novel yang mengantarkannya mendapatkan hadiah Nobel sepuluh tahun kemudian, 10 Desember 1957, La Peste. Saya membacanya baru-baru ini dalam versi bahasa inggris dengan judul The Plague, yang berarti wabah. Kisah yang bermula dari sebuah kota fiktif bernama Oran di Aljazair ini menceritakan datangnya wabah yang tiba-tiba, yang dimulai dari munculnya bangkai tikus pada bulan April sekitar tahun 1940-an. Secara sarkastik tapi relevan, Camus menulis dengan jenaka bahwa terhadap situasi ini masyarakat pada umumnya tidak perlu diperingatkan karena mereka mungkin tidak akan terlalu peduli, gagasan ini segera disetujui oleh para birokrat kota. Setingkat pejabat tinggi diyakinkan untuk menginformasikan bahwa virus ini hanya tanda bahaya palsu saja. Tidak perlu panik, gencarkan pariwisata. Lalu, para petugas publik di level bawah memberikan semacam testimoni bahwa ini adalah demam biasa saja. Hampir lima dasawarsa kemudian, eufemisme serupa rupanya muncul juga. Sebelum China melakukan Lockdown, peniup peluit pertama tanda bahaya bahkan dituduh penyebar hoaks. Warga Italia yang awalnya sangat longgar menjadi korban terburuk sebelum disusul Amerika. Ketika semakin banyak korban jatuh bergelimpangan, pemerintah di seluruh dunia dipaksa menelan pil pahit: tenaga medis terdidik berguguran di garda depan, pertumbuhan ekonomi rontok sembari menguras cadangan kas negara yang tidak sedikit. Virus ini menginfeksi lebih dari 2 juta orang, dengan ribuan orang meninggal dalam semalam. Sementara di Indonesia situasi pun tak kalah gawat. Pilihan juga terbatas: mudik atau pulang kampung?
Akan tetapi, dalam situasi yang paling suram sekalipun, selalu ada terang di ujung terowongan. Karya-karya sastra terbaik muncul dari kelamnya sejarah. Ia bercerita akan manisnya harapan. Suka cita hidup yang dijalani dengan penuh kebahagiaan. Setidaknya, begitulah cara penulis menampilkannya dalam karya-karya yang disajikan kepada pembaca. Tanpa harus menekuri kisah pribadi Enid Blyton yang tidak bahagia–rumah tangganya yang berantakan–masa kecil banyak anak di dunia, juga di Indonesia, tercerahkan dengan kehadiran Lima Sekawan dan atau Mallorie Tower. Dengan cara yang sama, bukankah demikian kita menikmati magnum opus Pram dalam masa-masa tahanannya di Pulau Buru?
Buku adalah sebuah sihir portabel yang unik, kata Stephen King. Melalui buku Karl May menulis tentang Winnetou dan petualangannya di dunia Barat yang liar– Melulu dikerjakan dari sebuah perpustakaan di Jerman. Seorang suami istri petualang Tony Wheeler dan Maureen Wheeler memberikan kabar menarik dari penjuru dunia yang jarang dijelajahi, tempat-tempat menarik, kadang terpencil, yang memancing banyak pelancong datang setelah membaca Lonely Planet. Sama halnya Andrea Hirata, melalui Laskar Pelangi, yang telah mengubah lanskap eksotisme Belitong yang semula bergantung pada timah menjadi destinasi wisata favorit yang telah memiliki salah satu museum sastra pertama di Indonesia, Museum Kata. Huruf-huruf membentuk kata lalu menggerakkan dunia.
Seperti yang ditunjukkan Tomos Robertson, alias Tom Foolery, seorang penyair Inggris kelahiran Selandia Baru, kita berharap kisah virus ini akan berakhir dalam susunan kata-kata ajaib membentuk harapan dalam larik-larik puisi di dalam salah satu video cerita pengantar tidurnya yang viral, The Great Realisation.
“(dunia sebelum virus) pada mulanya adalah sebuah dunia limbah dan keajaiban, keberlimpahan dan kemiskinan, jauh sebelum kita memahami apa yang terjadi pada 2020. Banyak orang muncul dengan sejumlah perusahaan dan menjual apa pun ke setiap jengkal tanah.
Tapi, di luar perkiraan, mereka tumbuh makin besar.
Kita selalu memiliki apa yang kita impikan, akan tetapi sekarang teramat cepat.
Kalian mendapatkan banyak hal yang diimpikan dalam sehari, dan cuma sekali klik.
Kita melihat banyak keluarga telah berhenti berkomunikasi.
Bukan berarti mereka tak pernah bicara. Tetapi makna bicara telah punah dan keseimbangan bekerja dan hidup pun berantakan.
Lalu mata anak-anak menjadi lebih kotak dan setiap balita memiliki telepon pintar.
Mereka memilah ketaksempurnaan, akan tetapi di antara pikuk-keramaian, mereka selalu kesepian.
setiap hari langit berubah semakin gelap, sampai kita tak menemukan gemintang.
Lalu kita mengangkasa bersama pesawat untuk menemukan bintang-bintang, sementara di daratan kendaraan saling berdesakan.
Kita berkeliling mengemudi sepanjang hari, hingga lupa rasanya berlari.
Kita membabat rerumput dan menggantinya dengan aspal. Mengerdilkan tetaman hingga tak bersisa.
Kita memenuhi lautan dengan plastik karena sampah tak pernah bisa diwadahi.
Sampai suatu ketika kalian memancing, ikan-ikan tertangkap kail sudah dalam keadaan terbungkus rapi.
Dan sementara kita mabuk, merokok dan berjudi, para pemimpin mengajarkan kita mengapa, tidak perlu menangisi kebijakan, mati bahkan mungkin jauh lebih baik.
Akan tetapi pada 2020, sebuah virus baru lahir. Pemerintah bertindak dan meminta kita sembunyi.
Dan saat setiap orang sembunyi, di antara ketakutan, insting mereka kembali, lalu mulai mengingat rasanya tersenyum.
kita mulai bertepuk tangan menyampaikan terima kasih, dan menghubungi orang terkasih, ibu.
Ketika kunci kendaraan mulai berdebu, kita lebih berharap dapat berlari kembali.
Saat tak banyak pesawat mengudara, bumi mulai bernapas lega.
pantai-pantai membawa kembali satwa liar yang semula melarikan diri jauh ke lautan
beberapa orang mulai menari, menyayi, memanggang kue.
Kita telah begitu terbiasa mendengar kabar buruk, tetapi berita-berita baik tengah berderap.
Dan saat kita menemukan obat lalu diperbolehkan keluar rumah,
semua orang berharap dunia yang baru tetap adanya, tidak seperti bumi yang rusak yang kita tinggalkan sebelum musim wabah.
Kebiasaan lama punah, dan setiap orang melatih kebiasaan baru.
Dan setiap tindakan kebaikan mendapatkan imbalannya.”
Pada cerita Tom Foolery, Jerapah (ziraffe) Peter Zilahy, alfabet terakhir yang mengakhiri kamus novelnya, terlihat berlari gembira di sepanjang sabana Afrika. Barangkali jerapah itu, atau mungkin kita, perlu berterima kasih kepada Ratu Corona yang memiliki kode sandi Covid-19.
post scriptum:
Puisi ini saya terjemahkan secara bebas, beberapa bagian larik puisi tidak saya sertakan, dengan suntingan seperlunya di beberapa tempat. (salman)

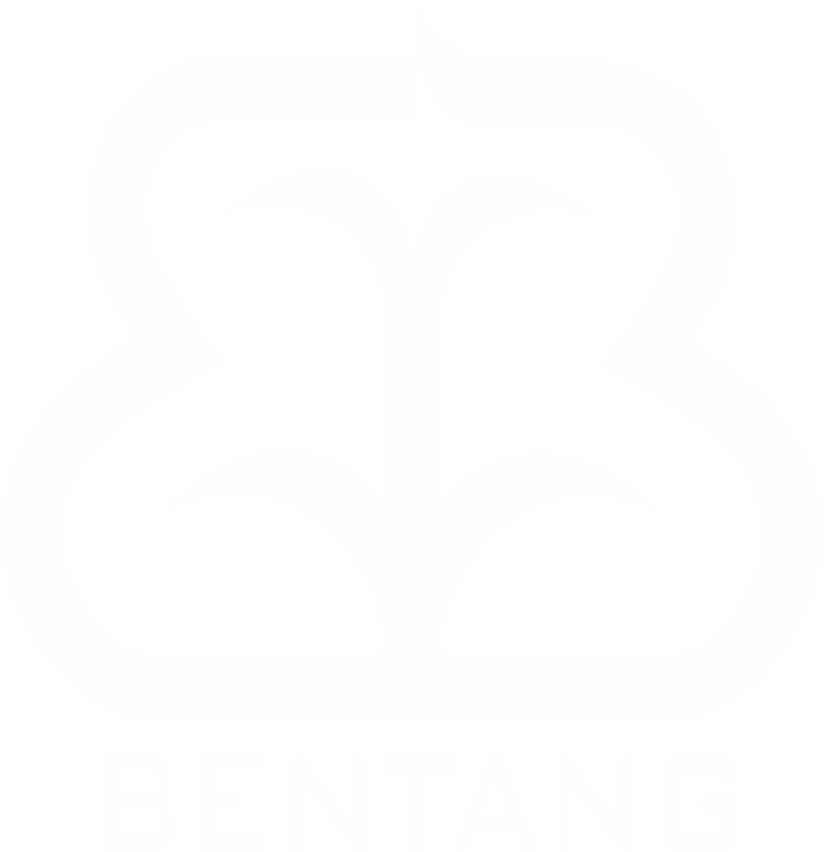







Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!