Geliat Komikus Lokal di Panggung Nasional
Medio awal 2000-an saya terjerumus ke dalam aktivitas baru yang menantang sekaligus kurang pengalaman. Setelah melepas pekerjaan sebagai jurnalis di sebuah redaksi dot.com di Bandung, saya nyemplung ke dunia penerbitan. Di sinilah untuk pertama kalinya saya langsung ditugasi menggarap sebuah acara serasa reality show yang dilabeli Pengadilan Komik. Ada kesan bahwa komik bersalah sehingga perlu diadili, padahal isu yang saat itu dimajukan adalah pentingnya membangun mental percaya diri para local genius di Indonesia ketika bertanding melawan produk-produk komik impor.
Hampir bisa dipastikan bahwa tema utama Mizan Komik ketika itu, awal karir saya adalah editor yunior merangkap proofreader di Divisi Anak dan Remaja (DAR) Mizan, adalah budaya tanding. Terma yang populer dinarasikan Emha dalam salah satu bukunya Terus Mencipta Budaya Tanding, memang relevan dengan arah perjuangan komik Mizan yang kala itu bermaksud mempersenjatai wawasan ideologis para komikus. Gaya ilustrasi tirus dan tajam khas manga misalnya, tidak menjadi kewajiban agar diterima ngomik di Mizan. Bahkan, banyak di antaranya didorong untuk menghasilkan gaya visual berbeda sehingga akan tampil sisi unik dan karakternya yang kuat. Cerita Panji Koming karya Dwi Koendoro, dan seri cerita 1001 malam adalah di antara komik-komik yang berhasil mencapai pembaca tanpa perlu diadili gaya visualnya.
Lazim pula ditemukan medio 2000-an itu untuk mengelabui pembaca kelahiran 80-an yang besar dalam buaian Doraemon dan Nobita atau Candy-Candy, komikus lokal dengan kemampuan menggambar manga yang sempurna memiliki nama pena kejepang-jepangan. Sah saja sebagai strategi market, apalagi menghadapi pembaca yang susah menerima gaya visual berbeda selain bergaya jepang. Yang menarik, bagi para konservasionis (yaitu mereka yang nguri-uri gaya komik atau ilustrasi sezaman dengan Ganes TH, Teguh Karya, dan lainnya), bahasa visual yang sudah mapan saat itu cenderung ditahbiskan menjadi gaya asli ilustrasi indonesia. Padahal urut-urutannya sesungguhnya tidak persis orisinil juga. Salah seorang legenda komik Indonesia, RA Kosasih misalnya pernah membuat komik yang terinpsirasi oleh Wonder Woman, yang dijudulinya Sri Asih. Kita juga bisa melihat kemiripan Gundala karya Hasmi dengan The Flash. Atau Godam dengan Batman. Ini semua adalah contoh serapan kreatif yang terjadi sebelum pada akhirnya dimapankan dan dilabeli visual “aseli” Indonesia. Bedanya, komikus veteran menyerapnya dari gaya visual Barat terutama Amerika atau Eropa.
Lima belas tahun sesudah perang tanding ideologis lokal versus impor, diskursus komik sekarang tidak lagi meruncing di kutub-kutub karya asli dengan visual khas indonesia atau bukan. Tampaknya selain pembaca semakin matang, keahlian para komikus Indonesia pun sudah tak lagi memikirkan populer di kancah nasional. Banyak komikus muda bergeliat dan menapaki karir mapan menekuni komik-komik yang dikerjakan untuk perusahaan besar internasional seperti Marvel, DC Comics, Top Cow dan banyak lagi. Di antara yang bersinar setelah menjadi alumni Mizan komik adalah sebuah studio komik profesional yang berkibar di bilangan Jakarta milik Chris Lee, alumni ilmu arsitektur Institut Teknologi Bandung, dan pernah berkibar bersama rekan-rekan sesama jurusannya dengan nama Studio Bajing Loncat. Karya monumental mereka adalah Ophir, terbit sekitar tahun 2002-2004.
Sebagai medium kreatif, komik tak lagi dibatasi oleh panjang halaman seperti harus mencapai ketebalan minimal 160 halaman yang sesungguhnya teramat sulit diselesaikan sebagai sebuah produk tunggal. Tersedianya kanal digital sebagai medium kreativitas yang powerful, membuat komikus leluasa mengunggah banyak artwork dalam aneka platform; dinikmati dalam bentuk web, atau dibuka melalui aplikasi. Lahirlah local genius baru yang besar dalam komunitas maya yang besar. Disukai, dibagi di antara sesama pembaca komik, dan perlahan membentuk fan base yang fanatik. Kekuatan ini semakin besar ketika difasilitasi secara sangat serius oleh Wahyu Aditya melalui Hello Fest, sebuah festival kreatif untuk merayakan gagasan visual komik, animasi, serta festival kostum yang menarik. Tidak kurang sebanyak 15000 orang berkerumun setiap tahunnya di Istora Senayan jakarta. Tentu saja kredit yang sama perlu kita sampaikan kepada banyak festival lainnya yang bergerilya dari kampus ke kampus atau dari kota ke kota.
Kini nama-nama lokal dengan karya menasional bahkan internasional semakin sering kita dengar dan jumpai. Komikus seperti Nurcholis yang memenangkan pernghargaan bergengsi di Jepang untuk karyanya Only Human menjadi dian bagi banyak calon kreator lainnya yang ingin menapaki jejak karir di wilayah yang sama. Jangan pula kita lupa bahwa Chris Lee, pendiri Caravan, termasuk yang mengerjakan salah satu episode G.I Joe besutan Marvel Comics. Jika kita cukup telaten mengumpulkan para kreator muda ini, bukan tidak mungkin masih banyak pekerja kreatif lainnya yang berada di balik nama-nama besar studio komik internasional.
Medio awal 2000-an saya terjerumus ke dalam aktivitas baru yang menantang sekaligus kurang pengalaman. Setelah melepas pekerjaan sebagai jurnalis di sebuah redaksi dot.com di Bandung, saya nyemplung ke dunia penerbitan. Di sinilah untuk pertama kalinya saya langsung ditugasi menggarap sebuah acara serasa reality show yang dilabeli Pengadilan Komik. Ada kesan bahwa komik bersalah sehingga perlu diadili, padahal isu yang saat itu dimajukan adalah pentingnya membangun mental percaya diri para local genius di Indonesia ketika bertanding melawan produk-produk komik impor.
Hampir bisa dipastikan bahwa tema utama Mizan Komik ketika itu, awal karir saya adalah editor yunior merangkap proofreader di Divisi Anak dan Remaja (DAR) Mizan, adalah budaya tanding. Terma yang populer dinarasikan Emha dalam salah satu bukunya Terus Mencipta Budaya Tanding, memang relevan dengan arah perjuangan komik Mizan yang kala itu bermaksud mempersenjatai wawasan ideologis para komikus. Gaya ilustrasi tirus dan tajam khas manga misalnya, tidak menjadi kewajiban agar diterima ngomik di Mizan. Bahkan, banyak di antaranya didorong untuk menghasilkan gaya visual berbeda sehingga akan tampil sisi unik dan karakternya yang kuat. Cerita Panji Koming karya Dwi Koendoro, dan seri cerita 1001 malam adalah di antara komik-komik yang berhasil mencapai pembaca tanpa perlu diadili gaya visualnya.
Lazim pula ditemukan medio 2000-an itu untuk mengelabui pembaca kelahiran 80-an yang besar dalam buaian Doraemon dan Nobita atau Candy-Candy, komikus lokal dengan kemampuan menggambar manga yang sempurna memiliki nama pena kejepang-jepangan. Sah saja sebagai strategi market, apalagi menghadapi pembaca yang susah menerima gaya visual berbeda selain bergaya jepang. Yang menarik, bagi para konservasionis (yaitu mereka yang nguri-uri gaya komik atau ilustrasi sezaman dengan Ganes TH, Teguh Karya, dan lainnya), bahasa visual yang sudah mapan saat itu cenderung ditahbiskan menjadi gaya asli ilustrasi indonesia. Padahal urut-urutannya sesungguhnya tidak persis orisinil juga. Salah seorang legenda komik Indonesia, RA Kosasih misalnya pernah membuat komik yang terinpsirasi oleh Wonder Woman, yang dijudulinya Sri Asih. Kita juga bisa melihat kemiripan Gundala karya Hasmi dengan The Flash. Atau Godam dengan Batman. Ini semua adalah contoh serapan kreatif yang terjadi sebelum pada akhirnya dimapankan dan dilabeli visual “aseli” Indonesia. Bedanya, komikus veteran menyerapnya dari gaya visual Barat terutama Amerika atau Eropa.
Lima belas tahun sesudah perang tanding ideologis lokal versus impor, diskursus komik sekarang tidak lagi meruncing di kutub-kutub karya asli dengan visual khas indonesia atau bukan. Tampaknya selain pembaca semakin matang, keahlian para komikus Indonesia pun sudah tak lagi memikirkan populer di kancah nasional. Banyak komikus muda bergeliat dan menapaki karir mapan menekuni komik-komik yang dikerjakan untuk perusahaan besar internasional seperti Marvel, DC Comics, Top Cow dan banyak lagi. Di antara yang bersinar setelah menjadi alumni Mizan komik adalah sebuah studio komik profesional yang berkibar di bilangan Jakarta milik Chris Lee, alumni ilmu arsitektur Institut Teknologi Bandung, dan pernah berkibar bersama rekan-rekan sesama jurusannya dengan nama Studio Bajing Loncat. Karya monumental mereka adalah Ophir, terbit sekitar tahun 2002-2004.
Sebagai medium kreatif, komik tak lagi dibatasi oleh panjang halaman seperti harus mencapai ketebalan minimal 160 halaman yang sesungguhnya teramat sulit diselesaikan sebagai sebuah produk tunggal. Tersedianya kanal digital sebagai medium kreativitas yang powerful, membuat komikus leluasa mengunggah banyak artwork dalam aneka platform; dinikmati dalam bentuk web, atau dibuka melalui aplikasi. Lahirlah local genius baru yang besar dalam komunitas maya yang besar. Disukai, dibagi di antara sesama pembaca komik, dan perlahan membentuk fan base yang fanatik. Kekuatan ini semakin besar ketika difasilitasi secara sangat serius oleh Wahyu Aditya melalui Hello Fest, sebuah festival kreatif untuk merayakan gagasan visual komik, animasi, serta festival kostum yang menarik. Tidak kurang sebanyak 15000 orang berkerumun setiap tahunnya di Istora Senayan jakarta. Tentu saja kredit yang sama perlu kita sampaikan kepada banyak festival lainnya yang bergerilya dari kampus ke kampus atau dari kota ke kota.
Kini nama-nama lokal dengan karya menasional bahkan internasional semakin sering kita dengar dan jumpai. Komikus seperti Nurcholis yang memenangkan pernghargaan bergengsi di Jepang untuk karyanya Only Human menjadi dian bagi banyak calon kreator lainnya yang ingin menapaki jejak karir di wilayah yang sama. Jangan pula kita lupa bahwa Chris Lee, pendiri Caravan, termasuk yang mengerjakan salah satu episode G.I Joe besutan Marvel Comics. Jika kita cukup telaten mengumpulkan para kreator muda ini, bukan tidak mungkin masih banyak pekerja kreatif lainnya yang berada di balik nama-nama besar studio komik internasional.
@salmanfaridibentang


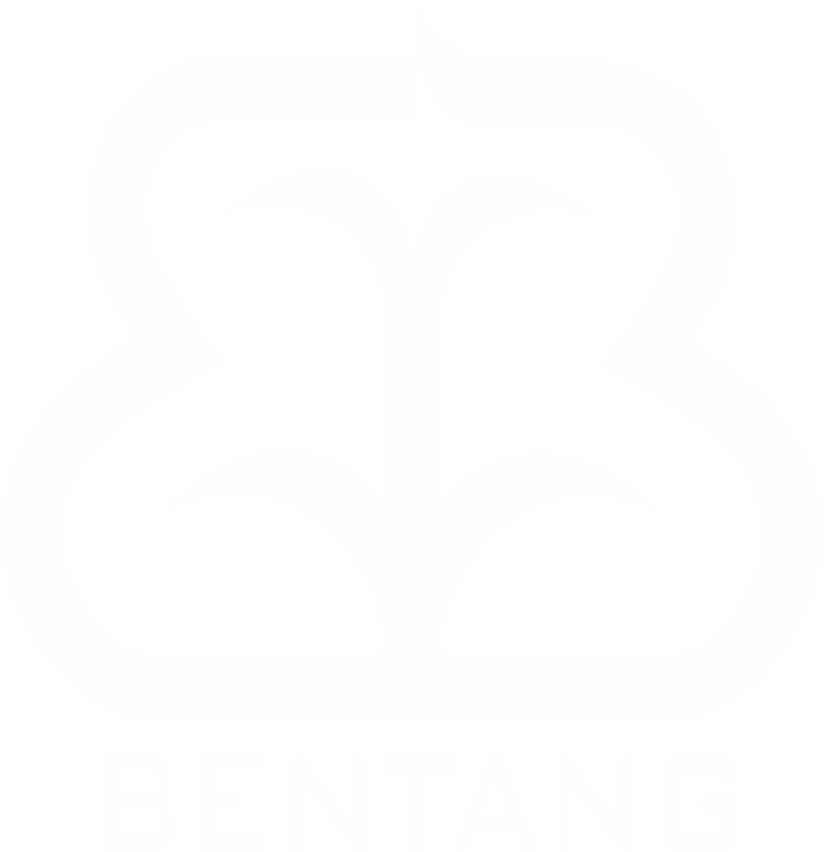





Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!