Belajar Menghayati Kehidupan bersama “Jatuh 7x Bangkit 8x”
Buku “Jatuh 7x Bangkit 8x” adalah kumpulan kisah kehidupan Sutarto, seorang anak dusun yang tumbuh menjadi guru hebat dan pribadi yang cerdas spiritual. Ditulis bersama Sumardianta, yang juga seorang guru hebat, buku ini menceritakan penghayatan Sutarto atas berbagai tantangan dalam hidupnya.
Terlahir di sebuah dusun kecil dalam keluarga yang serba-berkekurangan, Sutarto kenyang dengan pengalaman pahit. Dua tahun pertamanya di bangku SD dilalui dengan penuh ketakutan kepada guru yang bertangan besi. Ia dirisak (bully) oleh temannya yang tak hanya berbadan lebih besar, tetapi juga lebih kaya dan berkuasa di dusunnya. Di luar sekolah, kemiskinan mengharuskan Sutarto kecil dan saudara-saudaranya memanggul air berkilometer-kilometer selama musim tanam.
Sutarto bersaudara tak hanya iri dengan teman-temannya yang bisa bebas bermain, tetapi juga heran melihat bahwa ketika panen, buah yang bagus justru diberikan kepada Kepala Desa. Kemiskinan pula yang membuat Sutarto kecil suatu ketika harus berjalan berjam-jam menuntun kambing untuk dijual di pasar, hanya untuk mendapati kenyataan bahwa ia terlambat dan terpaksa melepas kambingnya dengan harga murah.
Sebagaimana tecermin pada judul buku, kisah-kisah Sutarto menegaskan pentingnya kegigihan di hadapan kesulitan dan tantangan hidup. Namun, hikmah yang hendak disampaikan lebih dalam daripada sekadar kemauan bangkit setelah terjatuh karena orang bisa menjadi gigih dengan penuh dendam. Berbagai ketidakadilan yang dialami Sutarto bisa saja membuatnya getir dan menyalahkan kehidupan (dunia di luar dirinya). Kegigihan bisa digerakkan oleh energi negatif untuk membalas dendam pada kehidupan yang memperlakukannya tidak adil. Dari beberapa kisah dalam buku ini, Sutarto tampaknya memang guru yang “keras” sekaligus welas hati dan menaruh harapan tinggi kepada anak-anak didiknya.
Mengapa Sutarto bisa mengatasi kemalangan dan tantangan, tanpa larut dalam kemarahan? Dari manakah sumber mindful awareness alias kemampuan menghayati tiap momen kehidupan yang ditunjukkan Sutarto? Dari berbagai kisah dalam buku ini, salah satu sumbernya adalah pertemuan Sutarto dengan guru-guru yang melihat anak didiknya sebagai manusia yang punya berbagai harapan dan ketakutan. Sutarto mengenang guru kelas IV-nya, Pak Rajimin, yang memanggilnya sekadar untuk mengobrol tentang keluarga dan apa yang dilakukannya setelah sekolah.
Obrolan-obrolan sederhana itu membuat Sutarto berani bertanya dan melontarkan pendapat di hadapan orang dewasa. Sutarto juga menceritakan guru kelas VI-nya yang membangkitkan cita-cita untuk meneruskan sekolah melalui cerita-cerita tentang muridnya yang mendapat beasiswa kuliah di IPB. Dalam bahasa para psikolog pendidikan aliran humanistik, guru-guru tersebut tak sekadar mengajar, tetapi juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan psikis muridnya yang paling dasar, seperti perasaan berguna dan perasaan menjadi bagian penting dari sebuah ikatan sosial.
Sumber kebijaksanaan yang kedua adalah kebaikan-kebaikan kecil dari sering kali datang dari orang tak dikenal. Sebagai contoh, Sutarto menceritakan kisahnya ketika harus mendaftarkan dirinya sendiri di SMP yang berjarak cukup jauh. Setelah mengayuh sepeda puluhan kilometer dalam perut kosong, Sutarto pulang tanpa berhasil mendaftar karena belum memiliki pasfoto. Dihardik sang ayah, Sutarto pun kembali ke SMP tersebut. Beruntung, ia bertemu petugas pendaftaran yang memperbolehkannya mendaftar meski tak memiliki pasfoto. Ini kebaikan kecil saja, tetapi betapa berbeda konsekuensinya jika sang petugas berkeras menegakkan aturan administratif tentang syarat pendaftaran.
Dalam fragmen lain, Sutarto menceritakan kebaikan hati seorang pedagang tempe yang rela meminjamkan uang untuk menutup kekurangan biaya menjahit celana seragam SMA-nya. Uang yang tak banyak, tetapi bisa membuat Sutarto percaya diri karena datang ke sekolah dengan pakaian terbaik yang pernah ia miliki. Sentuhan kebaikan-kebaikan kecil seperti inilah yang tampaknya membantu Sutarto meluruhkan energi negatif yang secara manusiawi muncul di hadapan kemalangan dan perlakuan tak adil yang bertubi-tubi.
Ketiga, kemauan untuk menghayati setiap momen kehidupan Sutarto tampaknya juga memiliki akar spiritual. Yang saya maksud bukanlah doktrin dan ritual-ritual agama, melainkan sikap atau keyakinan mendasar akan kebaikan sang Maha Agung, bahwa kehidupan yang Ia anugerahkan adalah sumber pelajaran yang tak habis-habisnya. Sikap spiritual inilah yang tampaknya menyiapkan Sutarto untuk mengambil hikmah dari pengalaman-pengalaman yang bagi orang lain akan tampak remeh. Sikap spiritual ini juga yang membuat Sutarto bisa mengingat dengan begitu detail berbagai fragmen masa lalu yang menjadi sumber hikmah, seperti nama setiap guru dan kawan sekelasnya di SD.
Pesan utama para penulis buku ini adalah soal pentingnya kegagalan dan tantangan dalam hidup. Dari kacamata akademik, tantangan memang bagian esensial dari proses belajar. Tidak ada proses belajar tanpa kegagalan. Hal ini berlaku untuk pembelajaran yang sederhana, seperti naik sepeda dan berhitung, sampai yang kompleks seperti proses pembentukan jati diri. Lev Vygotsky, psikolog Rusia yang pemikirannya menjadi fondasi aliran sosio-kultural dalam psikologi pendidikan dan perkembangan, mengemukakan bahwa pertumbuhan mental hanya terjadi di wilayah tak nyaman yang menuntut seorang pembelajar untuk melakukan apa yang belum bisa ia lakukan. Penelitian-penelitian kontemporer psikolog kognitif Robert Bjork menunjukkan adanya “desirable difficulties” alias kesulitan-kesulitan tertentu yang justru harus diciptakan untuk memicu terbentuknya pengetahuan dan keterampilan baru.
Pesan tentang pentingnya tantangan ini terasa begitu kontras dengan narasi tentang berbagai ancaman zaman modern yang menghantui anak-anak. Ada tekanan begitu besar pada para orangtua untuk semaksimal mungkin melindungi anak-anaknya dari narkotika, “pergaulan bebas” dan pornografi, perisakan (bullying) di dunia nyata maupun maya, sampai bacaan/informasi yang dianggap bisa menggoyang iman. Meski sebagian dari ancaman-ancaman tersebut memang nyata, buku ini membuat saya bertanya-tanya di mana batas antara upaya melindungi yang sehat dan yang berlebihan?
Tidak ada jawaban yang mudah dan pasti untuk pertanyaan ini. Tapi setidaknya, kisah-kisah dalam buku ini mengingatkan agar dalam upaya melindungi anak-anak, kita tidak justru menghalangi tumbuhnya ketangguhan mental mereka.
Penulis adalah Anindito Aditomo, Ph.D.
Peneliti Psikologi Pendidikan, Fakultas Psikologi, Universitas Surabaya Buku “Jatuh 7x Bangkit 8x” adalah kumpulan kisah kehidupan Sutarto, seorang anak dusun yang tumbuh menjadi guru hebat dan pribadi yang cerdas spiritual. Ditulis bersama Sumardianta, yang juga seorang guru hebat, buku ini menceritakan penghayatan Sutarto atas berbagai tantangan dalam hidupnya.
Terlahir di sebuah dusun kecil dalam keluarga yang serba-berkekurangan, Sutarto kenyang dengan pengalaman pahit. Dua tahun pertamanya di bangku SD dilalui dengan penuh ketakutan kepada guru yang bertangan besi. Ia dirisak (bully) oleh temannya yang tak hanya berbadan lebih besar, tetapi juga lebih kaya dan berkuasa di dusunnya. Di luar sekolah, kemiskinan mengharuskan Sutarto kecil dan saudara-saudaranya memanggul air berkilometer-kilometer selama musim tanam.
Sutarto bersaudara tak hanya iri dengan teman-temannya yang bisa bebas bermain, tetapi juga heran melihat bahwa ketika panen, buah yang bagus justru diberikan kepada Kepala Desa. Kemiskinan pula yang membuat Sutarto kecil suatu ketika harus berjalan berjam-jam menuntun kambing untuk dijual di pasar, hanya untuk mendapati kenyataan bahwa ia terlambat dan terpaksa melepas kambingnya dengan harga murah.
Sebagaimana tecermin pada judul buku, kisah-kisah Sutarto menegaskan pentingnya kegigihan di hadapan kesulitan dan tantangan hidup. Namun, hikmah yang hendak disampaikan lebih dalam daripada sekadar kemauan bangkit setelah terjatuh karena orang bisa menjadi gigih dengan penuh dendam. Berbagai ketidakadilan yang dialami Sutarto bisa saja membuatnya getir dan menyalahkan kehidupan (dunia di luar dirinya). Kegigihan bisa digerakkan oleh energi negatif untuk membalas dendam pada kehidupan yang memperlakukannya tidak adil. Dari beberapa kisah dalam buku ini, Sutarto tampaknya memang guru yang “keras” sekaligus welas hati dan menaruh harapan tinggi kepada anak-anak didiknya.
Mengapa Sutarto bisa mengatasi kemalangan dan tantangan, tanpa larut dalam kemarahan? Dari manakah sumber mindful awareness alias kemampuan menghayati tiap momen kehidupan yang ditunjukkan Sutarto? Dari berbagai kisah dalam buku ini, salah satu sumbernya adalah pertemuan Sutarto dengan guru-guru yang melihat anak didiknya sebagai manusia yang punya berbagai harapan dan ketakutan. Sutarto mengenang guru kelas IV-nya, Pak Rajimin, yang memanggilnya sekadar untuk mengobrol tentang keluarga dan apa yang dilakukannya setelah sekolah.
Obrolan-obrolan sederhana itu membuat Sutarto berani bertanya dan melontarkan pendapat di hadapan orang dewasa. Sutarto juga menceritakan guru kelas VI-nya yang membangkitkan cita-cita untuk meneruskan sekolah melalui cerita-cerita tentang muridnya yang mendapat beasiswa kuliah di IPB. Dalam bahasa para psikolog pendidikan aliran humanistik, guru-guru tersebut tak sekadar mengajar, tetapi juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan psikis muridnya yang paling dasar, seperti perasaan berguna dan perasaan menjadi bagian penting dari sebuah ikatan sosial.
Sumber kebijaksanaan yang kedua adalah kebaikan-kebaikan kecil dari sering kali datang dari orang tak dikenal. Sebagai contoh, Sutarto menceritakan kisahnya ketika harus mendaftarkan dirinya sendiri di SMP yang berjarak cukup jauh. Setelah mengayuh sepeda puluhan kilometer dalam perut kosong, Sutarto pulang tanpa berhasil mendaftar karena belum memiliki pasfoto. Dihardik sang ayah, Sutarto pun kembali ke SMP tersebut. Beruntung, ia bertemu petugas pendaftaran yang memperbolehkannya mendaftar meski tak memiliki pasfoto. Ini kebaikan kecil saja, tetapi betapa berbeda konsekuensinya jika sang petugas berkeras menegakkan aturan administratif tentang syarat pendaftaran.
Dalam fragmen lain, Sutarto menceritakan kebaikan hati seorang pedagang tempe yang rela meminjamkan uang untuk menutup kekurangan biaya menjahit celana seragam SMA-nya. Uang yang tak banyak, tetapi bisa membuat Sutarto percaya diri karena datang ke sekolah dengan pakaian terbaik yang pernah ia miliki. Sentuhan kebaikan-kebaikan kecil seperti inilah yang tampaknya membantu Sutarto meluruhkan energi negatif yang secara manusiawi muncul di hadapan kemalangan dan perlakuan tak adil yang bertubi-tubi.
Ketiga, kemauan untuk menghayati setiap momen kehidupan Sutarto tampaknya juga memiliki akar spiritual. Yang saya maksud bukanlah doktrin dan ritual-ritual agama, melainkan sikap atau keyakinan mendasar akan kebaikan sang Maha Agung, bahwa kehidupan yang Ia anugerahkan adalah sumber pelajaran yang tak habis-habisnya. Sikap spiritual inilah yang tampaknya menyiapkan Sutarto untuk mengambil hikmah dari pengalaman-pengalaman yang bagi orang lain akan tampak remeh. Sikap spiritual ini juga yang membuat Sutarto bisa mengingat dengan begitu detail berbagai fragmen masa lalu yang menjadi sumber hikmah, seperti nama setiap guru dan kawan sekelasnya di SD.
Pesan utama para penulis buku ini adalah soal pentingnya kegagalan dan tantangan dalam hidup. Dari kacamata akademik, tantangan memang bagian esensial dari proses belajar. Tidak ada proses belajar tanpa kegagalan. Hal ini berlaku untuk pembelajaran yang sederhana, seperti naik sepeda dan berhitung, sampai yang kompleks seperti proses pembentukan jati diri. Lev Vygotsky, psikolog Rusia yang pemikirannya menjadi fondasi aliran sosio-kultural dalam psikologi pendidikan dan perkembangan, mengemukakan bahwa pertumbuhan mental hanya terjadi di wilayah tak nyaman yang menuntut seorang pembelajar untuk melakukan apa yang belum bisa ia lakukan. Penelitian-penelitian kontemporer psikolog kognitif Robert Bjork menunjukkan adanya “desirable difficulties” alias kesulitan-kesulitan tertentu yang justru harus diciptakan untuk memicu terbentuknya pengetahuan dan keterampilan baru.
Pesan tentang pentingnya tantangan ini terasa begitu kontras dengan narasi tentang berbagai ancaman zaman modern yang menghantui anak-anak. Ada tekanan begitu besar pada para orangtua untuk semaksimal mungkin melindungi anak-anaknya dari narkotika, “pergaulan bebas” dan pornografi, perisakan (bullying) di dunia nyata maupun maya, sampai bacaan/informasi yang dianggap bisa menggoyang iman. Meski sebagian dari ancaman-ancaman tersebut memang nyata, buku ini membuat saya bertanya-tanya di mana batas antara upaya melindungi yang sehat dan yang berlebihan?
Tidak ada jawaban yang mudah dan pasti untuk pertanyaan ini. Tapi setidaknya, kisah-kisah dalam buku ini mengingatkan agar dalam upaya melindungi anak-anak, kita tidak justru menghalangi tumbuhnya ketangguhan mental mereka.
Penulis adalah Anindito Aditomo, Ph.D.
Peneliti Psikologi Pendidikan, Fakultas Psikologi, Universitas SurabayaBentang

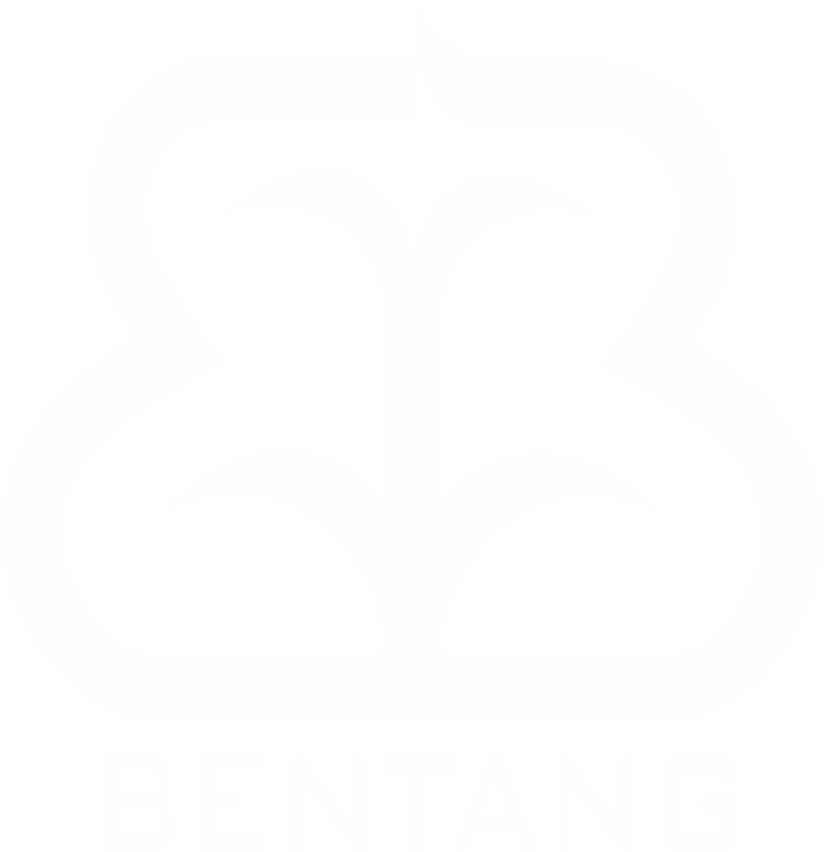





Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!