Mendidik Ikan Terbang
Beberapa hari lalu saya, dan banyak orangtua lainnya, menerima undangan pengumuman hasil belajar ujian tengah semester yang diolah berdasarkan kurikulum 2006. Undangan ini tentu dimaksudkan sebagai sistem evaluasi sekolah terhadap anak didik yang perlu diketahui orangtua. Semua nilai disusun, dan setiap anak diurutkan berdasarkan jumlah total yang diperoleh siswa dari semua mata pelajaran dimulai dari nilai paling besar. Yang paling buncit, meskipun tidak disebutkan paling bodoh, dimaklumi bersama sebagai anak yang kurang kompetitif dibandingkan puluhan teman lainnya.
Selama menunggu hasil evaluasi anak-anak, pihak sekolah berinisiatif menghadirkan profesional pelaku pendidikan yang memberikan perspektif belajar. Sayangnya, karena pemateri berafiliasi dengan lembaga pendidikan tertentu, metode pendidikan pun dikustomisasi berdasarkan teknik dan trik tertentu dalam menyelesaikan soal. Fokus yang berlebihan pada cara menjawab soal ini konon ditengarai menjadi penyakit pendidikan anak-anak kita sejak tingkat dasar. Mereka hanya perlu menjawab soal dengan benar, bukan memahami soal dengan benar.
Paulo Freire, tokoh pendidik yang membebaskan, melakukan kritik tajam bahwa dalam situasi di mana guru mengajar dan murid menerima pengetahuan, guru mengajar dan murid mendengarkan, mencatat dan mengingat, tak ubahnya sistem perbankan. Guru yang melakukan deposit, menyimpan sejumlah barang berharga, materi pengetahuan dan murid yang menerimanya. Atau, yang lebih buruk murid hanya semacam kontainer atau wadah yang melulu menerima apa pun yang diajarkan oleh gurunya. Apakah narasi ini keliru?
 Kritik Freire sesungguhnya ditujukan pada tidak adanya interaksi yang komunikatif antara guru dan murid. Sebab, pembelajaran yang sesungguhnya adalah mengeluarkan potensi terbaik anak didik yang sayangnya tidak semua nyaman dan berbakat dalam pelajaran eksakta saja. Matematika itu hanya satu kemampuan di antara banyak kemampuan lainnya. Siswa yang senang menulis dan meracik puisi, yang pandai dalam olah tubuh, berbakat dalam bermain musik dan banyak kemampuan lainnya seringkali agak terabaikan. Maka tidak heran jika olimpiade sains sering kali lebih bergaung dan lebih memiliki pamor dibandingkan kemampuan lainnya yang dikompetisikan, misalnya.
Kritik Freire sesungguhnya ditujukan pada tidak adanya interaksi yang komunikatif antara guru dan murid. Sebab, pembelajaran yang sesungguhnya adalah mengeluarkan potensi terbaik anak didik yang sayangnya tidak semua nyaman dan berbakat dalam pelajaran eksakta saja. Matematika itu hanya satu kemampuan di antara banyak kemampuan lainnya. Siswa yang senang menulis dan meracik puisi, yang pandai dalam olah tubuh, berbakat dalam bermain musik dan banyak kemampuan lainnya seringkali agak terabaikan. Maka tidak heran jika olimpiade sains sering kali lebih bergaung dan lebih memiliki pamor dibandingkan kemampuan lainnya yang dikompetisikan, misalnya.
Dalam metode pendidikan modern, Howard Gardner, penulis yang mencetuskan gagasan kecerdasan majemuk itu sejatinya menunjukkan jalan keluar memecahkan kebuntuan pendidikan yang lebih mengapresiasi wilayah otak kiri. Gardner memberikan harapan bahwa anak-anak kita terlahir spesial dan dalam diri mereka mengandung kecerdasan-kecerdasan spesifik yang berbeda dengan anak-anak lainnya. Contoh yang jamak kita baca adalah seekor ikan yang diajarkan kemampuan terbang seperti burung akan mengutuki sisa hidupnya sebagai makhluk yang bodoh!
Melalui kecerdasan majemuk, sebagai orangtua, kita dituntut untuk melihat kemampuan special setiap anak. Perlahan domain kecerdasan beranjak dari Intellectual Quotient (kecerdasan kognisi/intelektual) kepada Emotional Quotient (kecerdasan emosi). Perpindahan paradigma ini sekaligus menandai pentingnya kecerdasan yang berada dalam domain otak kanan setelah sekian lama didominasi oleh otak kiri. Meskipun sayangnya, Ibarat atlet, matematika tetap dilombakan sebagai salah satu dari 3 mata pelajaran utama untuk semua anak sekolah dasar di seluruh Indonesia. Maka siklus ikan belajar terbang pun setiap tahun berulang. Dan di banyak sekolah di mana para pendidiknya merasa siswa banyak yang tidak berbakat dalam matematika, mereka mengizinkan siswa mencontek atau lebih parahnya membagikan kunci jawaban sebelum ujian.
Maka, sedari dulu saya takjub dengan cerita Gadis Kecil di Pinggir Jendela. Kisah tentang seorang murid bernama Toto Chan yang menginspirasi metode belajar yang menarik. Di dalam kelas itu siswa belajar sambil bermain dan setiap anak memenangkan hal-hal istimewa sesuai kemampuan masing-masing. Sebagai orangtua tentu kita berharap sekolah memberikan yang terbaik untuk menarik keluar seluruh kemampuan terbaik anak-anak kita. Akan tetapi, sikap kita sebagai orangtua juga perlu dikoreksi, apalagi ketika kita merasa mampu membayar semua biaya pendidikan dan menyerahkan hasilnya semata pada sekolah dan atau lembaga pendidikan di luar sekolah. Perspektif yang benar, mula-mula, orangtua ikut bertanggung jawab dan terlibat agar anak-anak kita merasa nyaman dan gembira ketika sekolah, dan bukan diseret dari satu kursus ke kursus lainnya.
@salmanfaridi Beberapa hari lalu saya, dan banyak orangtua lainnya, menerima undangan pengumuman hasil belajar ujian tengah semester yang diolah berdasarkan kurikulum 2006. Undangan ini tentu dimaksudkan sebagai sistem evaluasi sekolah terhadap anak didik yang perlu diketahui orangtua. Semua nilai disusun, dan setiap anak diurutkan berdasarkan jumlah total yang diperoleh siswa dari semua mata pelajaran dimulai dari nilai paling besar. Yang paling buncit, meskipun tidak disebutkan paling bodoh, dimaklumi bersama sebagai anak yang kurang kompetitif dibandingkan puluhan teman lainnya.
Selama menunggu hasil evaluasi anak-anak, pihak sekolah berinisiatif menghadirkan profesional pelaku pendidikan yang memberikan perspektif belajar. Sayangnya, karena pemateri berafiliasi dengan lembaga pendidikan tertentu, metode pendidikan pun dikustomisasi berdasarkan teknik dan trik tertentu dalam menyelesaikan soal. Fokus yang berlebihan pada cara menjawab soal ini konon ditengarai menjadi penyakit pendidikan anak-anak kita sejak tingkat dasar. Mereka hanya perlu menjawab soal dengan benar, bukan memahami soal dengan benar.
Paulo Freire, tokoh pendidik yang membebaskan, melakukan kritik tajam bahwa dalam situasi di mana guru mengajar dan murid menerima pengetahuan, guru mengajar dan murid mendengarkan, mencatat dan mengingat, tak ubahnya sistem perbankan. Guru yang melakukan deposit, menyimpan sejumlah barang berharga, materi pengetahuan dan murid yang menerimanya. Atau, yang lebih buruk murid hanya semacam kontainer atau wadah yang melulu menerima apa pun yang diajarkan oleh gurunya. Apakah narasi ini keliru?
 Kritik Freire sesungguhnya ditujukan pada tidak adanya interaksi yang komunikatif antara guru dan murid. Sebab, pembelajaran yang sesungguhnya adalah mengeluarkan potensi terbaik anak didik yang sayangnya tidak semua nyaman dan berbakat dalam pelajaran eksakta saja. Matematika itu hanya satu kemampuan di antara banyak kemampuan lainnya. Siswa yang senang menulis dan meracik puisi, yang pandai dalam olah tubuh, berbakat dalam bermain musik dan banyak kemampuan lainnya seringkali agak terabaikan. Maka tidak heran jika olimpiade sains sering kali lebih bergaung dan lebih memiliki pamor dibandingkan kemampuan lainnya yang dikompetisikan, misalnya.
Kritik Freire sesungguhnya ditujukan pada tidak adanya interaksi yang komunikatif antara guru dan murid. Sebab, pembelajaran yang sesungguhnya adalah mengeluarkan potensi terbaik anak didik yang sayangnya tidak semua nyaman dan berbakat dalam pelajaran eksakta saja. Matematika itu hanya satu kemampuan di antara banyak kemampuan lainnya. Siswa yang senang menulis dan meracik puisi, yang pandai dalam olah tubuh, berbakat dalam bermain musik dan banyak kemampuan lainnya seringkali agak terabaikan. Maka tidak heran jika olimpiade sains sering kali lebih bergaung dan lebih memiliki pamor dibandingkan kemampuan lainnya yang dikompetisikan, misalnya.
Dalam metode pendidikan modern, Howard Gardner, penulis yang mencetuskan gagasan kecerdasan majemuk itu sejatinya menunjukkan jalan keluar memecahkan kebuntuan pendidikan yang lebih mengapresiasi wilayah otak kiri. Gardner memberikan harapan bahwa anak-anak kita terlahir spesial dan dalam diri mereka mengandung kecerdasan-kecerdasan spesifik yang berbeda dengan anak-anak lainnya. Contoh yang jamak kita baca adalah seekor ikan yang diajarkan kemampuan terbang seperti burung akan mengutuki sisa hidupnya sebagai makhluk yang bodoh!
Melalui kecerdasan majemuk, sebagai orangtua, kita dituntut untuk melihat kemampuan special setiap anak. Perlahan domain kecerdasan beranjak dari Intellectual Quotient (kecerdasan kognisi/intelektual) kepada Emotional Quotient (kecerdasan emosi). Perpindahan paradigma ini sekaligus menandai pentingnya kecerdasan yang berada dalam domain otak kanan setelah sekian lama didominasi oleh otak kiri. Meskipun sayangnya, Ibarat atlet, matematika tetap dilombakan sebagai salah satu dari 3 mata pelajaran utama untuk semua anak sekolah dasar di seluruh Indonesia. Maka siklus ikan belajar terbang pun setiap tahun berulang. Dan di banyak sekolah di mana para pendidiknya merasa siswa banyak yang tidak berbakat dalam matematika, mereka mengizinkan siswa mencontek atau lebih parahnya membagikan kunci jawaban sebelum ujian.
Maka, sedari dulu saya takjub dengan cerita Gadis Kecil di Pinggir Jendela. Kisah tentang seorang murid bernama Toto Chan yang menginspirasi metode belajar yang menarik. Di dalam kelas itu siswa belajar sambil bermain dan setiap anak memenangkan hal-hal istimewa sesuai kemampuan masing-masing. Sebagai orangtua tentu kita berharap sekolah memberikan yang terbaik untuk menarik keluar seluruh kemampuan terbaik anak-anak kita. Akan tetapi, sikap kita sebagai orangtua juga perlu dikoreksi, apalagi ketika kita merasa mampu membayar semua biaya pendidikan dan menyerahkan hasilnya semata pada sekolah dan atau lembaga pendidikan di luar sekolah. Perspektif yang benar, mula-mula, orangtua ikut bertanggung jawab dan terlibat agar anak-anak kita merasa nyaman dan gembira ketika sekolah, dan bukan diseret dari satu kursus ke kursus lainnya.
@salmanfaridiSalman Faridi

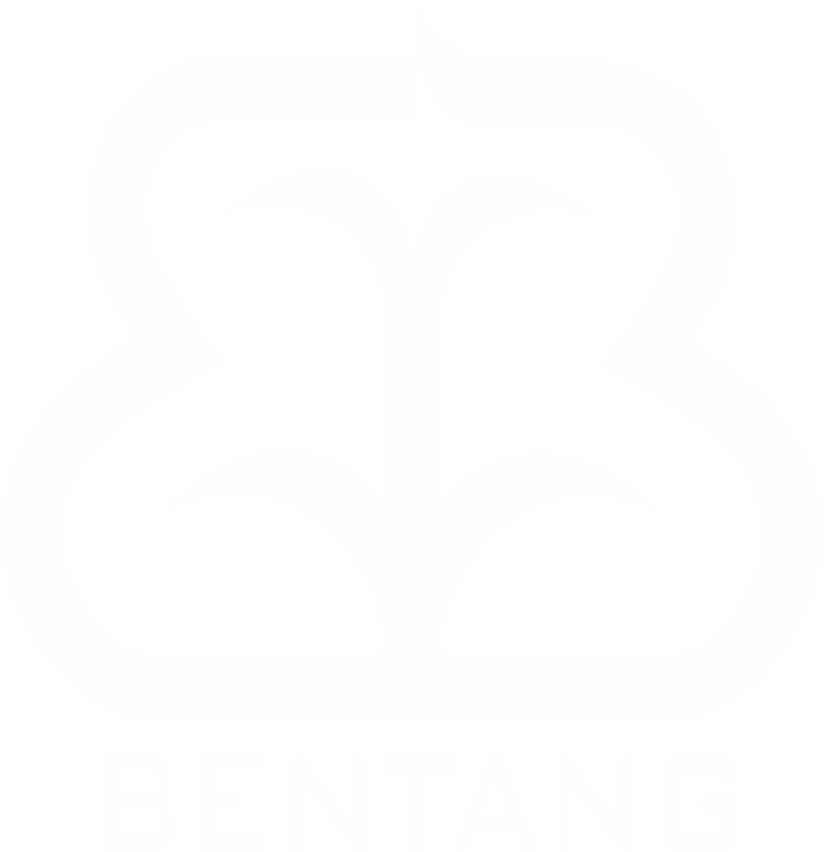





Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!